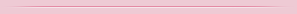Perdamaian dalam Perspektif al-Qur’an dan Bible (Upaya membangun dialog antar agama di Indonesia)
Pengantar
Akhir-akhir ini hubungan antar umat beragama di Indonesia kembali diuji. Penyerangan terhadap kelompok ahmadiyah, pembakaran gereja, demostrasi anarkis, hingga penyerangan terhadap jamaah gereja, peledakan bom, hingga teror-teror yang mengarah pada isu hubungan antar agama. Apa yang terjadi selama ini sangat mengiris nurani kemanusiaan. Bagaimana tidak, kasus penyerangan terhadap jamaah ahmadiyah di Cikeusik baru-baru ini misalnya memperlihatkan bagaimana bringas dan kejinya mereka melakukan kekerasan, ketika diantara jamaah sudah babak belur dan meninggalpun masih juga dipukul bahkan ditelanjangi bak seorang penjahat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan negeri yang plural dan majemuk ini? Sudah hilangkah rasa kemanusiaan sehingga kekerasan seolah sudah menjadi hal yang lumrah? Adakah sesuatu yang salah dalam ajaran agama?
Pertanyaan-pertanyaan diatas terus menerus menggelayut di benak penulis. Bagaimana mungkin seorang yang beragama justru menjadi “preman” yang siap untuk menyerang siapa saja yang berbeda agama dan keyakinan. Apakah religiusitas seseorang justru akan menghantarkannya menjadi seorang yang membenci orang lain yang berbeda agama. Kegelisahan-kegelisahan ini membuat penulis mencoba untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep perdamaian yang ada dalam ajaran agama (dalam hal ini adalah Islam dan Kristen) serta bagaimana konsep perdamaian itu diterapkan dalam kehidupan pemeluknya.
Perdamaian dalam Perspektif Al-Qur’an
Perdamaian merupakan salah satu ajaran pokok dalam ajaran Islam. Perintah untuk selalu berdamai tidak hanya terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an tetapi juga dicontohkan langsung dalam kehidupan Rosulullah Saw. Sebagaimana diketahui Muhammad adalah sosok yang sangat dikenal dengan kepribadian dan budi pekertinya yang baik. Ada banyak peristiwa bersejarah yang memperlihatkan pribadi Rasulullah sebagai seorang juru damai. Bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi. Banyak perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Muhammad selama menjalankan misi dakwahnya dimana hal tersebut bertujuan untuk menghindari konflik dan berupaya membangun perdamaian. Mulai dari perjanjian Hudaibiyah, piagam Madinah, Perjanjian dengan delegasi Najran dan masih banyak lagi.
Kata Islam sendiri juga diambil dari kata “salama” yang berarti selamat dan juga “silm dan salaam” (damai) yang secara jelas menegaskan bahwa karakter dasar dari ajaran Islam adalah menyebarkan perdamaian.
Dalam ungkapan teks agama, perdamaian sering dibahaskan dengan al-aman, Dalam terminologi al-amān, adalah sebuah kesepakatan untuk menghentikan peperangan dan pembunuhan dengan pihak musuh. Selain al-aman, masih ada beberapa istilah lain yang juga merujuk pada perdamaian yakni al-sulh, al-hudnah, al-mu’ahadah dan aqd al-zimmah. Banyak ayat-ayat di dalam al-Qur’an yang menunjukkan ajaran perdamaian. Meski diantara ayat-ayat tersebut tidak secara eksplisit menyatakan perintah perdamaian akan tetapi secara tersirat ayat tersebut mengajak umat muslim untuk membuat perdamaian. Misalnya ayat-ayat tentang berbuat adil, larangan untuk berbuat kekerasan[1], serta ayat-ayat tentang hubungan antar agama[2] serta universalitas agama.
Jika melihat teks-teks yang ada dalam al-Qur’an, maka akan terlihat wajah Islam yang damai dan menjadi penebar kedamaian. Dalam ayat tentang universalitas agama misalnya, terlihat bahwasanya Islam mengakui adanya pluralitas[3]. Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak memaksakan kehendak dalam beragama[4]. Bahkan Islam juga mengajarkan bagaimana cara berhubungan dengan pemeluk agama lain. Ungkapan salam yang selalu diucapkan oleh kaum muslimin tidak hanya sekedar ucapan salam tetapi lebih dari itu, yakni merupakan perintah untuk selalu menebarkan perdamaian dimanapun berada. Namun demikian dalam tataran praktis wajah damai Islam yang merupakan salah ajaran yang paling penting dalam agama Islam ini sering dinodai oleh praktik-praktik kekerasan dan pemaksaan oleh beberapa oknum dengan mengatasnamakan agama dan dengan dalih amar ma’ruf nahi mungkar. Sebuah konsep dakwah yang diwajibkan bagi setiap umat muslim. Prilaku-prilaku demikian ini membuat wajah Islam dinodai dan dipersepsikan sebagai agama kekerasan. Sebagaimana yang ditulis oleh Max Weber bahwa Islam adalah agama yang memiliki etos keprajuritan, tetapi tidak memiliki etos kewiraswastaan. Penyebaran Islam bahkan sering difahami dengan gambaran seseorang yang “memegang al-Quran di tangan kanan dan pedang di tangan kirinya”. Pendapat Max Weber ini memang tidak “sepenuhnya salah” ketika melihat prilaku radikalisme agama di kalangan kaum muslimin sehingga berwujud pada munculnya kekerasan serta pemaksaan dalam beragama. Namun pendapat ini jelas merupakan pendapat yang sangat tidak diterima ketika melihat secara menyeluruh ajaran Islam serta ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur’an. Artinya jelas bukan ajaran Islam yang memiliki etos keprajuritan karena sesungguhnya Islam adalah agama perdamaian.
Dalam mengajarkan perdamaian, ayat-ayat di dalam al-Qur’an tidak banyak menyebut kata perdamaian secara eksplisit, akan tetapi banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik dan menekankan adanya keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia dimana jika ajaran-ajaran ini dilakukan dengan baik tentu saja akan berimplikasi pada perdamaian di dunia. Perintah atau anjuran berbuat baik kepada sesama adalah modal awal membangun perdamaian. Perbuatan baik kepada sesama adalah pintu utama dalam mewujudkan perdamaian. Perdamaian tidak akan tercipta dengan kezaliman karena akan selalu muncul perlawanan dari orang yang dizalimi. Ibarat kata pepatah, semut pun akan marah jika diinjak. Oleh karena itu, perintah Islam kepada umatnya agar beramal saleh merupakan fondasi bagi terwujudnya perdamaian dunia.
Dalam perintah dalam shalat misalnya, sebagai bentuk ibadah tertinggi dalam Islam. Shalat dimulai dengan takbir, yaitu menjunjung tinggi Asma Allah menhunjam erat ke dalam jiwa sang pelaku. Maka shalat adalah bentuk dzikir (mengingat Allah) tertinggi, yang dengannya seorang Muslim merasakan kedamaian bathin yang tak terhingga. Namun kedamaian jiwa tidak berakhir, tetapi harus diteruskan dengan kedamaian yang lebih luas, yaitu kedamaian sosial. Untuk itu, shalat tak akan menjadi valid ketika tidak diakhiri dengan komitmen menyebarkan perdamaian kepada sesama. Salam yang diucapkan di akhir shalat adalah bentuk komitmen tertinggi dari seorang Muslim dalam mewujudkan perdamaian sosial.
Demikianlah konsep damai yang ada dalam al-Qur’an. Semua ajaran, perintah yang ada dalam ajaran Islam sebenarnya berujung pada terciptanya perdamaian dan keadilan di dunia. Kedatangan Islam di tengah bangsa arab yang pada masa itu jelas mempunyai misi perdamaian. Bangsa Arab yang saat itu terpecah belah kedalam suku-suku dan suka berperang menjadi sebuah satu komunitas dibawah konsep keumatan. Sehingga semua manusia disamakan kedudukannya kecuali atas dasar iman. Disinilah kemudian kedatangan Islam membawa pergeseran yang cukup fundamental dalam system sosial bangsa Arab dari yang awalnya terpusat pada pertalian atas dasar kekeluargaan menjadi pertalian atas dasar keimanan dibawah konsep ummat[5].
Muhammad Abduh dalam al-Islam wa al-Nashraniyyah: bayn al-’Ilm wa al-Madaniyyah juga menulis bahwa ajaran perdamaian Islam mewujud dalam struktur kekuasaan. Sebab dalam sejarah kekuasaan Islam, utamanya pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ditemukan sejumlah orang-orang Yahudi dan Kristen yang menjadi bendahara, sekretaris, tim dokter, bahkan penasehat raja. Ini tidak lain disemangati, bahwa dalam sistem kekuasaan sekalipun, perdamaian harus diutamakan, karena hampir tidak mungkin membangun tatanan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera tanpa basis perdamaian yang kuat[6]. Ini merupakan fakta sejarah Islam bagaimana sikap tasāmuh (toleran) dan kasih sayang kaum muslimin terhadap pemeluk agama lain, baik yang tergolong ke dalam ahl al-Kitab maupun kaum mushrik, bahkan terhadap seluruh makhluk, Islam mendahulukan sikap kasih sayang, keharmonisan dan dan kedamaian[7].
Perdamaian dalam Perspektif Bible
Pesan damai sangat terasa bagi umat kristiani, Yesus sebagai tokoh sentral dalam agama Kristen senantiasa mengajarkan umatnya untuk cinta damai. Yesus tidak hanya dikenal sebagi juru selamat tetapi juga diberi gelar sebagai Raja damai karena Dia adalah seorang yang anti terhadap kekerasan. Banyak cerita yang menggambarkan betapa Yesus adalah sang juru damai, bahkan di dalam bible dapat dilihat baha tidak satupun ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus pernah mengajak orang untuk berperang. Diantara ajaran Yesus tentang perdamaian adalah Yesus mengajarkan untuk melawan kekerasan tanpa kekerasan. Ajaran melawan kekerasan tanpa kekerasan ini bukan berarti mengajarkan kepasrahan atau tanpa perlawanan, tetapi juga mengajarkan jalan ketiga misalnya dengan menggunakan kekuatan moral daripada kekuatan fisik, mencari alternatif lain daripada menggunakan kekerasan, tidak membalas dendam, dan lain sebagainya[8].
Ada banyak ayat di dalam bible yang menunjukkan secara jelas tertulis bagaimana perdamaian juga menjadi tujuan utama dari ajaran Yesus. Bible berbicara tentang keadilan, pentingnya pemberian maaf serta mengasihi sekalipun terhadap musuh dan lain sebagainya. Yesus sebagai pembawa pesan damai juga memberikan teladan kepada umatnya bagaimana konsep tentang perdamaian itu dipraktekkan dalam kehidupan. Satu-satunya cerita yang menceritakan bahwa Yesus marah adalah ketika Yesus mengambil cambuk dari tali dan mengusir pedagang-pedagang dan penukar uang di halaman Bait Allah[9]. Tindakan ini tentu saja sama sekali tidak membahayakan siapapun kecuali nyawanya sendiri, karena semenjak peristiwa tersebut para pejabat Yahudi sepakat untuk menghukum mati Yesus. Masih banyak lagi cerita-cerita tentang Yesus dalam mengajarkan perdamaian dimana hal tersebut membuat umat kristiani terinspirasi untuk senantiasa membawa membawa misi perdamaian di muka bumi.
Damai dalam pandangan agama kristiani merujuk pada kata eirene dalam bahasa Yunani atau syallom di dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan menjadi damai sejahtera. Damai tidak hanya berarti bahwa tidak ada perang, pertikaian atau kekacauan, tetapi suasana hati dan lingkungan masyarakat di mana hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan diri sendiri tenang, bahagia dan terbuka kepada sang pemberi damai.
Upaya membangun perdamaian sebagaimana pesan bible ini juga menginspirasi gereja katolik, dimana dalam peribadatan dilengakapi dengan saling menyampaikan salam damai. Pesan damai dalam bible juga menginspirasikan pacem in terris dalam salah satu ensiklik[10]. Pacem in Terris berarti damai di bumi. Ensiklik ini ditulis oleh Paus Yohanes XXIII dan diterbitkan pada tanggal 11 April 1963 yang hingga saat ini masih diperingati dan masih cukup relevan. Didalam Pacem in Terris disebutkan bahwa perdamaian bertumpu pada empat tiang penyangga, yakni kebenaran, keadilan, cinta dan kemerdekaan.
Kebenaran merupakan tiang pertama, karena temasuk di dalamnya pengakuan bahwa manusia itu bukan merupakan penentu dirinya sendiri melainkan bahwa dia dipanggil untuk memenuhi kehendak Tuhan, pencipta segalanya, yang merupakan Sang kebenaran mutlak. Dalam hubungan manusiawi, kebenaran itu mengandaikan ketulusan, yang merupakan syarat untuk saling percaya dan dialog menuju perdamaian.
Perdamaian tidak dapat terjadi tanpa keadilan, hormat kepada martabat dan hak perorangan. Tanpa keadilan baik dalam hubungan pribadi, sosial maupun internasional akan menyebabkan kekacauan dan kekacauan akan menyebabkan kekerasan di bumi. Keadilan juga harus dilengkapi dengan cinta. Dengan cinta, maka sesama manusia akan menjadi saudara, sehingga akan terjadi hubungan untuk saling berbagi baik dalam kesengsaraan maupun kegembiraan. Cinta juga akan membuat manusia untuk sanggup mengampuni dan memaafkan karena pengampunan adalah salah satu faktor yang penting dalam memulihkan perdamaian setelah pecah pertikaian.
Baik kebenaran, keadilan maupun cinta itu mengandaikan adalanya kemerdekaan sebagai salah satu sifat hakiki yang dimiliki dengan manusia. Kemerdekaan akan memungkinkan manusia untuk bertindak berdasarkan akalnya dan memikul tanggungjawab atas segala tindakannya sendiri, karena manusia secara pribadi akan bertanggung jawab dihadapan Tuhan atas segala tindakannya[11].
Dari sini sangat terlihat bagaimana perdamaian yang tertulis dalam teks bible itu kemudian coba dikembangkan oleh umat kristiani (katolik) dalam Pacem Terris, sehingga apa diajarkan oleh Yesus di dalam bible dapat dilaksanaan oleh para jemaat.
Lebih Jauh tentang Perdamaian dalam al-Qur’an dan Bible
Perdamaian tidak hanya bermakna damai dalam arti tidak dalam kondisi peperangan, tetapi perdamaian juga mencakup makna yang lebih luas, yakni suatu kondisi dimana sudah tidak ada lagi kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial. Perdamaian dalam konsep ini meliputi semua aspek tentang masyarakat yang baik, seperti: terpenuhinya hak asasi yang bersifat universal, kesejahteraan ekonomi, keseimbangan ekologi dan nilai-nilai pokok lainnya. Berdasarkan konsep ini, perdamaian bukan hanya merupakan masalah pengendalian dan pengurangan tercapainya semua aspek tersebut, namun perdamaian merupakan konsep yang cukup luas dan pencapaiannya membutuhkan proses yang panjang. Dari sini dapat dilihat bahwa baik di dalam al-Qur’an maupun dalam bible, perdamaian juga mencakup makna yang luas ini. Disana terdapat konsep keadilan, kasih sayang, hubungan antar agama hingga ayat-ayat yang menjelaskan pada tataran praktis bagaimana cara mengakhiri konflik, pentingnya pemberian maaf dan lain sebagainya.
Perdamaian dalam bahasa al-Qur’an disebut salam dan dalam bahasa bible disebut syalom, merupakan inti ajaran dari kedua agama baik Islam maupun Kristen. kedua kitab tersebut sama-sama mengajarkan bagaimana membangun perdamaian di muka bumi ini, meski dalam prakteknya banyak sekali terjadi konflik yang menyebabkan peperangan dan munculnya banyak kekerasan atas nama agama. Karena meski di dalam al-Qur’an dan bible terdapat banyak ayat-ayat yang mengajarkan perdamaian tetapi disana juga terdapat ayat-ayat tentang peperangan yang seringkali dijadikan landasan untuk melakukan peperangan dan kekerasan. Didalam al-Qur’an misalnya ayat-ayat tentang jihad seringkali dimaknai sebagai ayat perang, sehingga perintah untuk berjihad ditafsirkan sama dengan perintah untuk berperang. Padahal jihad mempunyai makna yang sangat luas dan tidak hanya bisa dimaknai dengan perang. Disinilah sebenarnya yang menjadi persoalan besar di kalangan umat baik Islam maupun Kristen. Persoalan penafsiran terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam al-Qur’an dan bible, sehingga memunculkan “persoalan” dalam tataran praktis di kalangan umatnya, padahal al-Qur’an dan bible sendiri justru malah memperingatkan umatnya untuk tidak saling membunuh dan berperang. Peperangan hanya diperbolehkan jika dalam kondisi untuk mempertahankan diri.
Disini sengaja penulis tidak berupaya untuk membuat komparasi diantara keduanya dan hanya sekedar memaparkan bagaimana sebenarnya konsep perdamaian itu dalam perspektif al-Qur’an dan Bible, karena pada dasarnya di dalam kedua kitab tersebut banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan perdamaian, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua ajaran agama tersebut sama-sama mengajarkan dan mengajak umatnya untuk senantiasa membuat perdamaian di muka bumi. Sang pembawa damai (Muhammad dan Yesus) juga sama-sama memberikan teladan bagaimana perdamaian dapat dicapai meski keduanya sama-sama harus mengalami berbagai pengalaman pahit untuk mewujudkan itu.
Perdamaian dalam konteks Pluralitas agama di Indonesia
Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah panjang perkembangan agama-agama dinodai dengan berbagai peperangan dan kekerasan. Sejarah memang banyak mencatat berbagai macam konflik dan perang di kalangan umat manusia, baik konflik antar suku, negara maupun konflik atas nama agama. Berapa banyak nyawa melayang dan dikorbankan karena tujuan-tujuan yang tidak semestinya. Dalam konflik atas nama agama misalnya, tercatat sebuah perang besar yang disebut dengan “the holy war” atau seringkali dikenal dengan perang salib yang masih meninggalkan trauma bagi sebagian besar pengikut agama baik Islam maupun Kristen. hingga saat ini. Selain itu berapa banyak kekerasan yang terjadi di berbagai belahan dunia yang juga melibatkan nama agama secara tidak langsung, seperti kekerasan yang terjadi di Bosnia, Palestina, Irlandia, hingga Irak yang membuat ada jarak dan sekat yang cukup lebar antar pemeluk agama[12].
Apa yang terjadi diatas juga terjadi di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang pluralis dan multikultur, dengan bermacam-macam agama, beragam budaya, suku, bahasa, pluralitas dan kemajemukan ini di satu sisi merupakan salah satu kekayaan bangsa yang cukup membanggakan, tetapi disisi lain jika pluralitas dan keragaman ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan menjadi konflik yang dapat memecah belah kesatuan bangsa ini.
Ada beberapa catatan tentang konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia, sebutlah konflik di Ambon, Poso, kasus terorisme, pembakaran gereja dan yang baru-baru ini terjadi kekerasan terkait dengan ahmadiyah. Kekerasan atas nama agama ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya kekerasan antar agama tetapi juga kekerasan diantara umat seagama. Hal ini bisa dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga diantaranya CRCS UGM, Wahid Institute yang menyatakan bahwa angka kekerasan berbasis agama dan diskriminasi terhadap aliran dan agama minoritas baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan dan keagamaan semakin meningkat[13].
Jika melihat pada teks-teks agama diatas (baca : al-Qur’an dan bible), maka ada semacam “jurang” atau “kesenjangan” antara apa yang ada dalam ajaran agama dengan apa yang telah dipraktekkan oleh para pemeluk agama. Dalam konteks Indonesia terutama dalam hal ini adalah umat Islam, dimana beragam stigma negatif muncul terkait dengan berbagai konflik dan kekerasan atas nama agama. Hal ini sungguh memprihatinkan –untuk tidak mengatakan memalukan-karena sebagai kelompok agama mayoritas bukannya bisa mengayomi kelompok minoritas tetapi justru malah menjadi penebar terror dan kekerasan.
Kekerasan atas nama agama seringkali diawali dengan perasaan curiga terhadap kelompok agama lain. Bagi kalangan muslim stigma bahwa umat kristiani pasti akan menggunakan beragam cara untuk mempengaruhi dan menyebarkan agamanya dan begitu juga sebaliknya bagi umat kristiani, stigma teroris dan preman berjubah membuat mereka tidak nyaman dengan kelompok muslim. Prejudice semacam ini sangat sulit untuk dihilangkan bahkan ada kalanya justru sengaja dipupuk sehingga menjadi semakin kuat. Hal inilah yang membuat hubungan antar agama seolah sulit menjadi harmonis.
Dari sinilah kemudian perlu adanya membangun sebuah dialog yang intensif antar pemeluk agama. Karena tanpa adanya dialog, saling mengenal antar berbagai pemeluk agama, upaya menghilangkan prasangka-prasangka tentu akan sulit dan selama prasangka-prasangka itu masih ada, maka benturan dan kekerasan antar agama akan terus terjadi.
Berbagai program dialog antar agama seringkali dimunculkan dalam rangka menjembatani berbagai agama ini[14]. Tetapi sampai saat ini dialog antar agama belum menyentuh pada masyarakat bawah yang notabene sebenarnya selalu menjadi korban dari kekerasan yang terjadi. Dialog antar agama hanya sekedar proyek yang cukup melibatkan kalangan atas dan intelektual. Hal inilah yang menyebabkan dialog antar agama mengalami kebuntuan tanpa memberikan kontribusi. Dialog antar agama tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, tetapi juga bagi kaum intelektual dan para tokoh agama. Karena tanpa peran kaum intelektual dan agamawan maka dialog antar agama secara luas dan intensif tidak akan terlaksana. Proses dialog yang dilakukan secara terus menerus akan membawa dampak bagi terciptanya perdamaian. Perdamaian yang selalu didambakan semua pihak.
Penutup
Ajaran agama sesungguhnya adalah ajaran tentang perdamaian. Namun demikian, pada kenyataannya, apa yang telah diajarkan dalam agama tidak selalu sama dengan apa yang telah dipraktekkan oleh para pemeluknya. Berbagai kekerasan atas nama agama masih terus saja terjadi. Semua bersikukuh sebagai pihak yang benar. Begitu mudahnya isu terkait dengan agama disulut dan memecah perdamaian.
Semua ini terjadi karena masing-masing pemeluk agama mempunyai prasangka dan kecurigaan terhadap pemeluk agama lain. Disinilah kemudian perlu adanya dialog antar umat beragama. Dialog yang terbangun dan dilakukan secara terus-menerus tidak hanya di kalangan atas tetapi juga di masyarakat kalangan bawah. Dengan terbangunnya dialog maka prasangka dan perasaan curiga yang selama ini mengungkung pemeluk agama dan menghalangi toleransi perlahan-lahan akan semakin terbuka, sehingga dengan sendirinya perdamaian akan tercapai.
Daftar Pustaka
Armstrong, Karen, Berperang Demi Tuhan, (Jakarta: Serambi dan Mizan, 2001), cet-II.
Dumartheray, Roland dkk, Agama dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2003, cet-2.
Harold Coward and Gordon S Smith (ed.), Religion and Peacebuilding, (USA : State University of NewYork, 2004.
Harun, Hermanto Islam dan Perdamaian dalam http://ibnuharun.multiply.com/journal/item/12
Muhaimin AG (ed.), Damai di dunia Damai untuk Semua Perspektif berbagai Agama, Jakarta : Proyek Peningkatan Pengkajian Hidup Umat Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004.
Suherlan, Ian, Menegakkan Perdamaian dan Keadilan, Buletin No. 185, http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A4473_0_3.
Wahid, Abdurrahman dkk, Dialog : Kritik dan Identitas Agama, Yogyakarta: Dian Interfidei, t.th.
[1] QS Adz-Dzariyat [51]: 56
[2] QS Al-Kafirun 1-6
[3] QS al-Hujurat [49]: 13
[4] QS Al-Baqarah 256
[5] Harold Coward and Gordon S Smith (ed.), Religion and Peacebuilding, (USA : State University of NewYork, 2004), hlm 130-131
[6] Ian Suherlan, Menegakkan Perdamaian dan Keadilan, Buletin No. 185, http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A4473_0_3.
[7] Hermanto Harun, Islam dan Perdamaian dalam http://ibnuharun.multiply.com/journal/item/12
[8] Muhaimin AG (ed.), Damai di dunia Damai untuk Semua Perspektif berbagai Agama, (Jakarta : Proyek Peningkatan Pengkajian Hidup Umat Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004), hlm 130-147
[9] Yohanes 2 : 13-25
[10] Istilah ensilik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani egkyklios, kyklos yang berarti edaran. Pada dasarnya itu adalah surat edaran. Sekarang ini istilah itu dipergunakan didalam kalangan gereja katolik untuk menunjuk pada surat-surat Paus yang disampaikan kepada umat katolik.
[11] Muhaimin AG (ed.), Op.Cit, hlm 166-167
[12] Lihat Karen Armstrong, Berperang Demi Tuhan, (Jakarta: Serambi dan Mizan, 2001), cet-II.
[13] tentang laporan keberagaman di Indonesia tahun 2010 oleh CRCS UGM bisa dilihat di www.crcs.ugm.ac.id, laporan kebebasan agama yang dibuat oleh The Wahid Institute tahun 2010 bisa dilihat di www.wahidinstitute.org.
[14] Roland Dumartheray dkk, Agama dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2003), cet-2. Lihat juga Abdurrahman Wahid dkk, Dialog : Kritik dan Identitas Agama, (Yogyakarta: Dian Interfidei, t.th)
1 komentar Februari 12, 2011
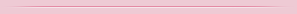
Bermain Bersama
Oleh: Zunly Nadia
Hari minggu Togar, Joko dan Dito asyik bermain perang-perangan. Mereka menggunakan pistol buatan sendiri yang terbuat pelepah daun pisang. “Door, door, door, teriak Togar begitu mendapati Joko bersembunyi di balik pohon.
Mendengar teriakan teman-temannya yang sedang bermain, Maria yang berada di rumah tidak jauh dari tempat mereka bermainpun tertarik untuk ikut bermain bersama mereka. “Teman-teman aku ikut maen perang-perangan ya?” kata Maria. “Kamu kan anak perempuan, kalau anak perempuan itu maen boneka aja” kata Togar. “Iya Maria, anak perempuan gak boleh maen perang-perangan” sahut Dito. “Tapi aku kan pengen juga maen tembak-tembakan, karena besok kalau sudah besar aku bercita-cita pengen jadi tentara” jawab Maria. Mendengar keributan kecil diantara anak-anak itu, paman dolit yang sedang mencuci motor di dekat mereka akhirnya ikut berbicara. “Eh anak-anak, semua permainan itu sama, boleh dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. Maria boleh main tembak-tembakan seperti kalian, begitu juga kalian, anak laki-laki boleh main masak-masakan”. Mendengar teguran dan nasehat dari paman dolit, akhirnya mereka kembali bermain bersama dan kali ini Maria ikut bergabung dengan Togar, Joko dan Dito untuk main perang-perangan. .
Add a comment Januari 27, 2011
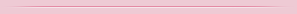
Temanku berbeda agama
Oleh : Zunly Nadia
Sore hari Widi, Ihsan, dan Saka bermain-main di lapangan di dekat rumah mereka. Tidak seperti biasanya Petrus yang selalu bermain bersama mereka kali ini tidak ada. “Petrus kemana ya widi kok ga datang?” Kata Ihsan, “Iya kan gak seru kalo gak ada Petrus” sahut Saka. “Wah aku juga gak tahu kemana Petrus” jawab Widi. “Kalo gitu gimana kalau kita pergi ke rumah Petrus, siapa tahu dia sedang sakit” lanjut Widi.
Kemudian Widi, Ihsan dan Saka pergi ke rumah Petrus. Sesampai di rumah Petrus mereka melihat Petrus beserta adiknya sedang sibuk mendekorasi rumahnya. “Petrus lagi ngapain?” tanya Ihsan, Hai temen-temen, kebetulan kalian kesini, aku dan adikku sedang menghias rumah karena sebentar lagi kami akan memperingati hari raya Natal. “Kalau begitu boleh dong kita bantu menghias” kata Widi, “Wah senang sekali kalau kalian mau membantu menghias rumah” kata Petrus.
Akhirnya Ihsan, Widi dan Saka ikut serta menghias rumah petrus yang akan merayakan hari raya agamannya. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka senang sekali bisa membantu menghias pohon natal, memasang gambar-gambar sinterklaus yang lucu, serta hiasan-hiasan lain yang di tembok ruang tamu rumah Petrus. Perbedaan dalam beragama ternyata tidak menghalangi Ihsan, Saka, Widi dan Petrus untuk bersahabat dan bermain bersama.
Add a comment Januari 27, 2011
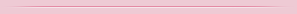
Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif Amin Abdullah dan Relevansinya bagi ilmu-ilmu Keagamaan.
oleh: Zunly Nadia
Pengantar
Jargon integratif-interkonektif memang cukup populer di dengar terutama bagi kalangan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jargon ini tidak hanya sekedar jargon pasca peralihan IAIN menjadi UIN tetapi lebih dari itu menjadi core values dan paradigma yang akan dikembangkan UIN Sunan Kalijaga yang mengisyaratkan tidak ada lagi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Gagasan integratif-interkonektif ini muncul dari mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Amin Abdullah yang kemudian mengaplikasikannya dalam pengembangan IAIN menjadi UIN.
Gagasan keilmuan yang integratif dan interkonektif ini muncul dari sebuah “kegelisahan” pak Amin terkait dengan tantangan perkembangan zaman yang sedemikian pesatnya yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Teknologi yang semakin canggih sehingga tidak ada lagi sekat-sekat antar bangsa dan budaya, persoalan migrasi, revolusi IPTEK, genetika, pendidikan, hubungan antar agama, gender, HAM dan lain sebagainya. Perkembangan zaman mau tidak mau menuntut perubahan dalam segala bidang tanpa tekecuali pendidikan keislaman, karena tanda adanya respon yang cepat melihat perkembangan yang ada maka kaum muslitimin akan semakin jauh tertinggal dan hanya akan menjadi penonton, konsumen bahkan korban di tengah ketatnya persaingan global. Menghadapi tantangan era globlalilasi ini, umat Islam tidak hanya sekedar butuh untuk survive tetapi bagaimana bisa menjadi garda depan perubahan. Hal ini kemudian dibutuhkan reorientasi pemikiran dalam pendidikan Islam dan rekonstruksi sistem kelembagaan.
Jika selama ini terdapat sekat-sekat yang sangat tajam antara “ilmu” dan “agama” dimana keduanya seolah menjadi entitas yang berdiri sendiri dan tidak bisa dipertemukan, mempunyai wilayah sendiri baik dari segi objek-formal-material, metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan hingga institusi penyelenggaranya. Maka tawaran paradigma integratif-interkoneksi berupaya mengurangi ketegangan-ketegangan tersebut tanpa meleburkan satu sama lain tetapi berusaha mendekatkan dan mengaitkannya sehingga menjadi “bertegus sapa” satu sama lain[1].
Dalam makalah ini, penulis berusaha untuk mendalami dan memaparkan lebih jauh bagaimana paradigma integratif-interkonektif ini dibangun dan bagaimana relevansinya bagi ilmu-ilmu keagamaan serta implikasinya ketika paradigma ini coba diterapkan di IAIN yang saat ini berubah menjadi UIN.
Mengenal Sosok M Amin Abdullah
M. Amin Abdullah lahir di Margomulyo, Tayu, Pati, Jawa Tengah, 28 Juli 1953. Pada 1972, dia menamatkan pendidikan menegah di Kulliyat al-Mu’allimin al-Islamiyyah (KMI), Pesantren Gontor, Ponorogo, yang kemudian dilanjutkan dengan Program Sarjana Muda (Bakalaureat) pada Institut Pendidika Darusslam(IPD)1977 di pesantren yang sama.[2] M. Amin Abdullah dalah Guru Besar Filsafat Islam Pada Fakultas Ushuluddin IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dikukuhkan pada tanggal 13 Mei 2000, menyelesaikan S1 Jurusan Perbandingan Agama di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1981, menyekesaikan studi S3 (Program Ph.D) pada METTU (Middle East Technical University), Departemen of Philosopy, Fakulty of Art and Sciences, Ankara Turki tahun 1990,[3] dengan disertasinya, “The Idea of Universality of Ethical Normas in Ghazali and Kant”, diterbitkan di Turki (Ankara: Turkiye Diyanet Vakfi, 1992).[4] Mengikuti program Post Doktoral di McGill University, Montreal Canada selama enam bulan (Oktober 1997s/d Februari 1998). Dan Sejak tahun 2001 hingga tahun 2010 menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.[5] Sebuah karir tertinggi dalam bidang akademis, setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai pembantu rektor I yang membawahi bidang akademik serta asisten direktur program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Amin dikenal sebagai salah satu pakar dalam Islamic studies, banyak karya-karyanya yang telah dibukukan menjadi rujukan bagi para akademisi. Disertasinya, The Idea of University of Ethical Norms in Ghazali and Kant, diterbitkan di Turki (Ankara: Turkiye Diyanet Vakfi, 1992). Karya-karya ilmiah lainnya yang diterbitkan, antara lain: Falsafah Kalam di Era Postmodernisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995); Studi Agama: Normativitas atau Historisitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Dinamika Islam Kultural : Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer, (Bandung, Mizan, 2000); Antara al-Ghazali dan Kant : Filsafat Etika Islam, (Bandung: Mizan, 2002) serta Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005). Sedangkan karya terjemahan yang diterbitkan adalah Agama dan Akal Pikiran: Naluri Rasa Takut dan Keadaan Jiwa Manusiawi (Jakarta: Rajawali, 1985); Pengantar Filsafat Islam: Abad Pertengahan (Jakarta: Rajawali, 1989).
Selain karya-karyanya yang telah dibukukan, tulisan-tulisannya juga dapat dijumpai di berbagai jurnal keilmuan, antara lain Ulumul Qur’an (Jakarta), Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies (Yogyakarta) dan beberapa jurnal keilmuan keislaman yang lain. Di samping itu, dia aktif mengikuti seminar di dalam dan luar negeri. Seminar internasional yang diikuti, antara lain: “Kependudukan dalam Dunia Islam”, Badan Kependudukan Universitas Al-Azhar, Kairo, Juli 1992; tentang “Dakwah Islamiyah”, Pemerintah Republik Turki, Oktober 1993; Lokakarya Program Majelis Agama ASEAN (MABIM), Pemerintah Malaysia, di Langkawi, Januari 1994; “Islam and 21st Century”, Universitas Leiden, Belanda, Juni 1996; “Qur’anic Exegesis in the Eve of 21st Century”, Universitas Leiden, Juni 1998, ”Islam and Civil Society : Messages from Southeast Asia“, Tokyo Jepang, 1999; “al-Ta’rikh al- Islamy wa azamah al-huwaiyah”, Tripoli, Libia, 2000; “International anti-corruption conference”, Seol, Korea Selatan, 2003; Persiapan Seminar “New Horizon in Islamic Thought”, London, Agustus, 2003; “Gender issues in Islam”, Kualalumpur, Malaysia, 2003; “Dakwah and Dissemination of Islamic Religious Authority in Contemporarry Indonesia, Leiden, Belanda, 2003.
Dalam organisasi masyarakat dia menjadi Ketua Divisi Ummat, ICMI, Orwil Daerah Istimewa Yogyakarta, 1991-1995. Setelah Muktamar Muhammadiyah ke-83 di Banda Aceh 1995, diberi amanat sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1995-2000). Kemudian terpilih sebagai salah satu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wakil Ketua (2000-2005)[6].
Pemikiran M Amin Abdullah : dari Normativitas-historisitas menuju Integratif-interkonektif
Jika dilihat dari karya-karyanya, setidak-tidaknya ada dua pemikiran besar Amin Abdullah yang pada dasarnya kedua-duanya merupakan respon dari konteks dan persoalan yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin. Pertama adalah persoalan pemahaman terhadap keislaman yang selama ini dipahami sebagai dogma yang baku, hal ini karena pada umumnya normativitas ajaran wahyu ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis. Pendekatan ini berangkat dari teks kitab suci yang pada akhirnya membuat corak pemahaman yang tekstualis dan skripturalis.
Sedangkan disisi lain untuk melihat historisitas keberagamaan manusia, pendekatan sosial keagamaan digunakan melalui pendekatan historis, sosiologis, antropologis dan lain sebagainya, yang bagi kelompok pertama dianggap reduksionis. Kedua pendekatan ini bagi Amin Abdullah merupakan hubungan yang seharusnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua jenis pendekatan ini – pendekatan yang bersifat teologis-normatif dan pendekatan yang bersifat histories-empiris ini sangat diperlukan dalam melihat keberagamaan masyarakat pluralistik. Kedua pendekatan ini akan saling mengoreksi, menegur dan memperbaiki kekurangan yang ada pada kedua pendekatan tersebut. Karena pada dasarnya pendekatan apapun yang digunakan dalam studi agama tidak akan mampu menyelesaikan persoalan kemanusiaan secara sempurna. Pendekatan teologis-normatif saja akan menghantarkan masyarakat pada keterkungkungan berfikir sehingga akan muncul truth claim sehingga melalaui pendekatan histories-empiris akan terlihat seberapa jauh aspek-aspek eksternal seperti aspek sosial, politik dan ekonomi yang ikut bercampur dalam praktek-praktek ajaran teologis[7].
Di sinilah, Amin Abdullah berusaha merumuskan kembali penafsiran ulang agar sesuai dengan tujuan dari jiwa agama itu sendiri, dan di sisi yang lain mampu menjawab tuntutan zaman, dimana yang dibutuhkan adalah kemerdekaan berfikir, kreativitas dan inovasi yang terus menerus dan menghindarkan keterkungkungan berfikir. Keterkungkungan berfikir itu salah satu sebabnya adalah paradigma deduktif, dimana meyakini kebenaran tunggal, tidak berubah, dan dijadikan pedoman mutlak manusia dalam menjalankan kehidupan dan untuk menilai realitas yang ada dengan “hukum baku” tersebut.
Sedangkan yang kedua adalah paradigma keilmuan integratif-interkonektif. Paradigma ini juga dibangun sebagai respon atas persoalan masyarakat saat ini dimana era globalilasi banyak memunculkan kompleksitas persoalan kemanusiaan. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, paradigma keilmuan integratif dan interkonektif ini merupakan tawaran yang digagas oleh Amin Abdullah dalam menyikapi dikotomi yang cukup tajam antara ilmu umum dan ilmu agama. Asumsi dasar yang dibangun pada paradigma ini adalah bahwa dalam memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun baik ilmu agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Kerjasama, saling membutuhkan dan bertegur sapa antar berbagai disiplin ilmu justru akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia, karena tanpa saling bekerjasama antar berbagai disiplin ilmu akan menjadikan narrowmindedness.
Secara aksiologis, paradigma interkoneksitas menawarkan pandangan dunia manusia beragama dan ilmuwan yang baru, yang lebih terbuka, mampu membuka dialog dan kerjasama serta transparan. Sedangkan secara antologis, hubungan antar berbagai disiplin keilmuan menjadi semakin terbuka dan cair, meskipun blok-blok dan batas-batas wilayah antar disiplin keilmuan ini masih tetap ada. Lebih lanjut tentang paradigma interkonektif dan integratif ini akan penulis paparkan di bawah ini.
Mengenal lebih jauh tentang Paradigma Integratif-Interkonektif dan Relevansinya bagi ilmu-ilmu keagamaan
Apa yang terjadi selama ini adalah dikotomi yang cukup tajam antara keilmuan sekuler dan keilmuan agama (baca ilmu keislaman). Keduanya seolah mempunyai wilayah sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain. Hal ini juga berimplikasi pada model pendidikan di Indonesia yang memisahkan antara kedua jenis keilmuan ini. Ilmu-ilmu sekuler dikembangkan di perguruan tinggi umum sementara ilmu-ilmu agama dikembangkan di perguruan tingga agama. Perkembangan ilmu-ilmu sekuler yang dikembangkan oleh perguruan tinggi umum berjalan seolah tercerabut dari nilai-nilai akar moral dan etik kehidupan manusia, sementara itu perkembangan ilmu agama yang dikembangkan oleh perguruan tinggi agama hanya menekankan pada teks-teks Islam normative, sehingga dirasa kurang menjawab tantangan zaman. Jarak yang cukup jauh ini kemudian menjadikan kedua bidang keilmuan ini mengalami proses pertumbuhan yang tidak sehat serta membawa dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan keagamaan di Indonesia[8].
Selain dikotomi yang tajam antara kedua jenis keilmuan ini, tantangan berat yang harus dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah perkembangan zaman yang demikian pesat. Era globalisasi yang seolah datang dengan perubahan yang cukup fundamental dimana sekat-sekat antar individu, bangsa seolah sudah tidak ada lagi sehingga memunculkan kompleksitas persoalan.
Paradigma integratif-interkonektif yang ditawarkan oleh Amin Abdullah ini merupakan jawaban dari berbagai persoalan diatas. Integrasi dan interkoneksi antar berbagai disiplin ilmu, baik dari keilmuan sekuler maupun keilmuan agama, akan menjadikan keduanya saling terkait satu sama lain, “bertegur sapa”, saling mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Dengan demikian maka ilmu agama (baca ilmu keislaman) tidak lagi hanya berkutat pada teks-teks klasik tetapi juga menyentuh pada ilmu-ilmu sosial kontemporer.
Dengan paradigma ini juga, maka tiga wilayah pokok dalam ilmu pengetahuan, yakni natural sciences,social sciences dan humanities[9] tidak lagi berdiri sendiri tetapi akan saling terkait satu dengan lainnya. Ketiganya juga akan menjadi semakin cair meski tidak akan menyatukan ketiganya, tetapi paling tidak akan ada lagi superioritas dan inferioritas dalam keilmuan, tidak ada lagi klaim kebenaran ilmu pengetahuan sehingga dengan paradigma ini para ilmuwan yang menekuni keilmuan ini juga akan mempunya sikap dan cara berfikir yang berbeda dari sebelumnya.
Hadarah al-‘ilm (budaya ilmu), yaitu ilmu-ilmu empiris yang menghasilkan, seperti sains, teknologi dan ilmu-ilmu yang terkait dengan realitas tidak lagi berdiri sendiri tetapi juga bersentuhan dengan hadarah al-falsafah sehingga tetap memperhatikan etika emansipatoris. Begitu juga sebaliknya, hadarah al-falsafah (budaya filsafat) akan terasa kering dan gersang jika tidak terkait dengan isu-isu keagamaan yang termuat dalam budaya teks dan lebih-lebih jika menjauh dari problem-problem yang ditimbulkan dan dihadapi oleh hadarah al-‘ilm.[10]
Skema Single Entity
Skema Isolated Entities
Skema Interconected Entities
Dari skema di atas tampak jelas bahwa ketiga keilmuan tersebut menjadi bentuk dialektika
atau tegur sapa. Hal inilah yangmenjadi tolak ukur signifikansi dalam penerapan integrasi-interkoneksi dalam keilmuan UIN Sunan Kalijaga.[11] Tiga demensi pengembangan keilmuan ini bertujuan untuk mempertemukan kembali ilmu-ilmu modern dengan ilmu-ilmu keislmanan (integrasi-interkoneksi).
Sementara itu, sebagaimana yang terlihat dalam jaring laba-laba diharapkan dengan paradigma integratif-interkonektif akan terjadi perkembangan dalam ilmu keislaman, dimana tidak lagi terfokus pada lingkar 1 dan lingkar ke 2 tetapi juga melangkah pada lingkar ke 3 dan ke 4. Selama ini pengajaran di perguruan tinggi agama masih berkutat pada lingkar 1 dan ke 2 dan masih baru akan memasuki lingkar ke 3 serta belum menyentuh pada lingkar ke 4. Jaring laba-laba ini menampakkan adanya pergerakan zaman dan kompleksitas persoalan masyarakat yang akan bisa diselesaikan dengan perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Lingkar 1 dan 2 disebut sebagai Ulumuddin yang merupakan representasi dari “tradisi lokal” keislaman yang berbasis pada “bahasa” dan “teks-teks” atau nash-nash keagamaan. Lingkar ke 3 disebut sebagai al-Fikr al-Islamiy sebagai representasi pergumulan humanitas pemikiran keislaman yang berbasis pada “rasio-intelek”. Sedangkan lingkar ke 4 disebut Dirasat Islamiyyah atau Islamic Studies sebagai kluster keilmuan baru yang berbasis pada paradigma keilmuan sosial kritis-komparatif lantaran melibatkan seluruh “pengalaman” (experiences) umat manusia di alam historis-empiris yang amat sangat beranekaragam[12].
Paradigma integrative-interkonektif ini terlihat sangat dipengaruhi oleh Abid al-Jabiri yang membagi epistemology Islam menjadi tiga, yakni epistemologi bayani, epistemologi burhani dan epistemologi irfani.[13] Berbeda dengan Abid al-Jabiri yang melihat epistemologi irfani tidak penting dalam perkembangan pemikiran Islam, bagi Amin Abdullah ketiga epistemologi seharusnya bisa berdialog dan berjalan beriringan. Selama ini epistemologi bayani lebih banyak mendominasi dan bersifat hegemonik sehingga sulit untuk berdialog dengan tradisi epistemology irfani dan burhani, pola pikir bayani ini akan bekembang jika melakukan dialog, mampu memahami dan mengambil manfaat sisi-sisi fundamental yang dimiliki oleh pola pikir irfani dan burhani[14]. Karenanya hubungan yang baik antara ketiga epistemologi ini tidak dalam bentuk pararel ataupun linier tetapi dalam bentuk sirkular. Bentuk pararel akan melahirkan corak epistemologi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya hubungan dan persentuhan antara satu dengan yang lain. Sedangkan bentuk linier akan berasumsi bahwa salah satu dari ketiga epistemologi menjadi “primadona”, sehingga sangat tergantung pada latar belakang, kecenderungandan kepentingan pribadi atau kelompok, sedangkan dengan bentuk sirkular diharapkan masing-masing corak epistemologi keilmuan dalam Islam akan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga dapat mengambil manfaat dari temuan-temuan yang ditawarkan oleh tradisi keilmuan lain dalam rangka memperbaiki kekurangan yang ada.[15]
Apa yang ditawarkan oleh Amin Abdullah dengan paradigma integratif-interkonektif secara konseptual memang sangat relevan bagi perkembangan keilmuan islam (Islamic Studies), dimana dialog antar disiplin ilmu akan semakin memperkuat keilmuan islam dalam menghadapi tantangan zaman dengan segala kompleksitas yang ada. Namun demikian apa yang telah digagas oleh Amin Abdullah ini ketika diaplikasikan dalam bentuk pendidikan model UIN menurut subyektifitas penulis menjadi tidak applicable dalam pengembangan studi islam, karena dalam hal ini tenyata pekembangan IAIN menjadi UIN –sekali lagi menurut pandangan penulis- justru semakin menyisihkan keilmuan agama dari ilmu alam dan sosial humaniora dan membuat ketidakjelasan. Hal ini bisa dilihat adanya kerancuan dalam program studi yang ditawarkan, ada sosiologi agama, ada sosiologi umum, ada psikologi dan psikologi agama, kemudian jika fakultas Ushuluddin akan membuka antropologi agama dan kemudian fakultas sosial humaniora juga akan membuka antropologi maka yang tejadi adalah ketidakjelasan yang justru akan merugikan banyak pihak terutama bagi out put dari produk UIN. Dalam hal ini bisa jadi kerancuan ini akibat belum “mapannya” epistemologi dalam keilmuan integratif-interkonektif yang digagas oleh Amin Abdullah ini. Dalam hal ini penulis curiga jangan-jangan paradigma yang dibangun oleh pak Amin ini hanya untuk dijadikan legitimasi dalam mengubah IAIN menjadi UIN dan bukan untuk kebutuhan pengembangan Islamic studies murni. Disini berbeda dengan terobosan pemikiran Amin Abdullah tentang historisitas dan normativitas dalam pendekatan studi agama yang selalu relevan baik dalam konsep maupun aplikasinya hingga saat ini, apalagi dalam konteks Indonesia saat ini dimana banyak muncul kelompok-kelompok Islam tekstualis-skripturalis dimana aspek historisitas dan normativitas seringkali sulit dibedakan atau bahkan aspek historisitas sengaja dilupakan.
Penutup
Paradigma baru yang dibangun oleh Amin Abdullah dengan integratif-interkonektif ini memang sangat relevan dengan kebutuhan zaman saat ini. Koneksitas ini diharapkan mampu menjawab kebuntuan dalam keilmuan islam dan lebih jauh lagi dapat menjawab kompleksitas problem kemanusiaan di era globalisasi. Namun paradigma ini tidak mudah untuk diaplikasikan, hal ini bisa dilihat ketika paradigma ini coba diterapkan dalam pengembangan perguruan tinggi agama yang mengejawantah dengan perubahan IAIN menjadi UIN ternyata banyak menimbulkan kerancuan terutama bagi program-program studi yang muncul kemudian, dan hal ini menurut harus segera dicarikan solusi, sehingga tujuan ideal dari integrasi dan interkoneksi ini dapat terwujud.
Daftar Pustaka
Abdullah, M. Amin, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integratif-Interkonektif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet II.
———————— ,-Pendidikan Agama Era Multikultural Multi Religius, Jakaarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
——————– , dkk., Seri Kumpulan Pidato Guru Besar: Rekonstruksi Metodologi Ilmu –ilmu keislaman,Yogyakarta: SUKA Press, 2003.
———————, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, cet-3.
————————-, Mempertautkan ‘Ulum al-din al-fikr al-islami dan dirasat islamiyah; sumbangan keilmuan Islam untuk peradaban global, disampaikan dalam Workshop Pembelajaran Inovatif Berbasis Integrasi-Interkoneksi, Yogyakarta, 19 Desember 2008
———————, Tafsir Baru Studi Eslam dalam Era Multikultural, Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50 dan Kurnia Alam Semesta, 2002.
Al-Jabiri, Muhammad Abid, Takwin al-‘Aql al-‘Araby, Beirut : al-Markaz al-Taqhafy al-‘Araby, 1990.
—————————–,Bunyah al-‘Aql al-Araby: Dirasat Tahliliyah Naqdiyyah li Nazm al-Ma’rifah fi al-Saqifah al-‘Arabiyah Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1990.
http://aminabd.wordpress.com/perihal/
[1] M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integratif-Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet II), hlm 92-93
[2] M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural Multi Religius (Jakaarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 191.
[3] M. Amin Abdullah, dkk., Seri Kumpulan Pidato Guru Besar: Rekonstruksi Metodologi Ilmu –ilmu keislaman (Yogyakarta: SUKA Press, 2003), hlm. 363.
[4]M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural…,hlm. 191-192.
[5] M. Amin Abdullah, dkk., Seri Kumpulan Pidato…hlm. 363.
[7] M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, cet-3), hlm v-18
[8] M. Amin Abdullah, Islamic Studies…, Op.Cit., hlm 92-94
[9]M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan…,hlm. 370.
[10]M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan…,hlm. 402-403.
[11] Mashudi, “Reintegrasi Epistemology Keilmuan…, hlm. 145.
[12] Pembatasan istilah Ulumuddin, al-Fikr al-Islamy dan Dirasat Islamiyah ini hanya akan mempermudah dalam pembahasan. Dalam pembagian ini Amin Abdullah merujuk pada perspektif sejarah perkembangan studi agama-agama yang telah melewati 4 (empat) fase, yaitu, lokal, kanonikal, kritikal dan global dari Keith Ward. Pertama, adalah tahapan Local. Semua agama pada era presejarah (Prehistorical period) dapat dikategorikan sebagai lokal. Semua praktik tradisi, kultur, adat istiadat, norma, bahkan agama adalah fenomena lokal. Fase kedua adalah fase Canonical atau Propositional. Era agama-agama besar dunia (world religions) masuk dalam kategori tradisi Canonical ini. Kehadiran agama-agama Ibrahimi (Abrahamic Religions), dan juga agama-agama di Timur, yang pada umumnya menggunakan panduan Kitab Suci (the Sacred Text) merupakan babak baru tahapan sejarah perkembangan agama-agama dunia. Dalam Islam, fase ini corak keberagamaan yang scripturalis-tekstualis. Fase ketiga adalah fase Critical. Pada abad ke-16 dan 17, kesadaran beragama di Eropa mengalami perubahan yang radikal, yang terwadahi dalam gerakan Enlightenment. Tradisi baru ini berkembang terus, yang kemudian membudaya dalam dunia akademis, penelitian (research), scholarly work dan wilayah intelektual pada umumnya. Dalam fase ini muncul keilmuan baru dalam Islam sebagaimana dalam lingkar ke 3 jaring laba-laba. Fase keempat adalah fase Global sebagaimana yang terjadi saat ini dan memunculkan keilmuan baru berikut juga metodenya yang lebih kritis dan tidak hanya terpaku pada rasio. Disini bisa terlihat pada lingkar ke 4 jaring laba-laba. Lebih lanjut lihat M. Amin Abdullah, Mempertautkan ‘Ulum al-din al-fikr al-islami dan dirasat islamiyah; sumbangan keilmuan Islam untuk peradaban global, disampaikan dalam Workshop Pembelajaran Inovatif Berbasis Integrasi-Interkoneksi, Yogyakarta, 19 Desember 2008
[13] Epistemologi bayani yang bersumber pada teks (wahyu), epistemologi bayani yang bersumber pada akal dan rasio dan epistemologi irfani yang bersumber pada pengalaman (experience). Lebih lanjut tentang ketiga epistemologi ini lihat Muhammad Abid al-Jabiri, Takwin al-‘Aql al-‘Araby, (Beirut : al-Markaz al-Taqhafy al-‘Araby, 1990), Bunyah al-‘Aql al-Araby: Dirasat Tahliliyah Naqdiyyah li Nazm al-Ma’rifah fi al-Saqifah al-‘Arabiyah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1990).
[14] M. Amin Abdullah dkk, Tafsir Baru Studi Eslam dalam Era Multikultural, (Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50 dan Kurnia Alam Semesta, 2002), hlm 13-14
[15] Ibid., hlm 28-33
2 komentar Januari 27, 2011
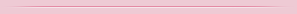
Signifikansi Hermeneutika dalam Tafsir al-Qur’an Kontemporer (Sebuah Pengantar)
Oleh : Zunly Nadia/SQH
Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan kemanusiaan juga berkembang semakin kompleks, mulai dari persoalan genetika, eksplorasi ruang angkasa, pendidikan, hubungan antar agama, persoalan gender, HAM, dan lain sebagainya, dimana hampir tidak ada lagi sekat-sekat yang antara manusia karena teknologi telah membuat semua orang diseluruh dunia berinteraksi dengan mudahnya. Pesatnya perkembangan zaman ini membuat ilmu-ilmu keIslaman mau tidak mau harus segera berbenah dan mengikuti arus zaman, dan tanpa terkecuali ilmu tafsir.
Ilmu tafsir juga dituntut untuk selalu berkembang dalam menghadapi kompleksnya persoalan kemanusiaan. Disinilah kemudian gagasan tentang penggunaan hermeneutika menjadi sebuah keniscayaan bagi para penafsir saat ini. Hermeneutika sebagai sebuah metodologi dalam tafsir al-Qur’an dirasa cukup penting dan mendesak untuk dilakukan karena hermeneutika tidak hanya berbicara dalam tataran teks semata melainkan juga mempertimbangkan konteks serta peran subyektifitas seorang penafsir, sehingga tafsir atau kajian terhadap al-Qur’an menjadi kontekstual dan bisa menjawab tantangan zaman.
Namun demikian kehadiran hermeneutik sebagai sebuah metode dalam menafsirkan teks al-Qur’an ini tidak diterima begitu saja dikalangan umat Islam dan justru menimbulkan reaksi bagi sebagian mereka. Bagi yang menolak hermeneutika sebagai salah satu metode dan metodologi dalam menafsirkan al-Qur’an, mereka beranggapan bahwa hermeneutika bukanlah berasal dari tradisi Islam dan merupakan metode yang dipakai dalam mengkaji bible, tentu saja mereka menolak, karena menggunakan hermeneutika dalam mengkaji al-Qur’an sama saja dengan mensejajarkan al-Qur’an dengan bible dan juga teks-teks yang lain seperti teks sastra dan lain sebagainya, padahal al-Qur’an adalah kalam ilahi dan bukan hasil karya cipta manusia.
Dalam makalah ini penulis mencoba akan memaparkan signifikansi hermeneutika dalam kajian tafsir al-Qur’an berikut ragam corak hermeneutika al-Qur’an yang dipakai oleh para penafsir al-Qur’an kontemporer.
Seputar Hermeneutika
Kata Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani “Hermeneuo” yang berarti menafsirkan. Kata ini sering diasosiasikan dengan nama salah satu dewa bagi manusia. Hermes adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia[1]. Hermeneutika secara ringkas biasa diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti. Lebih jelasnya jika melihat dari dari teminologinya, kata hermeneutika ini bisa didefinisikan menjadi sebagai tiga hal, yakni[2]:
- Pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir.
- Usaha pengalihan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca
- Pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.
Adapun pengasosiasian etimologis antara hermeneutik dengan hermes secara inhern menggambarkan suatu struktur triadic seni penafsiran, yaitu[3]:
- Tanda, pesan atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran yang diasosiasikan dengan pesan yang dibawa oleh Hermes.
- Perantara atau penafsir (Hermes),
- Penyampaian pesan itu oleh sang perantara agar bisa dipahami dan sampai kepada yang menerima.
Masih terkait dengan pengertian hermeneutik, Ben Vedder membedakan empat keberagaman dan kebertingkatan definisinya, sebagimana yang dikutp oleh Sahiron empat terma yang dimaksud adalah hermeneuse, hermeneutic, philosophical hermeneutics, dan hermeneutical philosophy[4].
Hermeneuse didefinisikan sebagai penjelasan atau interpretasi sebuah teks, karya seni dan prilaku seseorang. Dari definisi ini maka hermeneuse merujuk pada aktifitas penafsiran terhadap obyek-obyek tertentu seperti teks, symbol-simbol seni (lukisan, novel, puisi dan lain sebagainya) serta prilaku manusia. Disini hermeneuse tidak terkait secara substansial dengan metode-metode atau hal-hal yang melandasi penafsiran.
Sementara itu hermeneutik merupakan aturan, metode, strategi atau langkah penafsiran, sedangkan Philosophical hermeneutics tidak lagi berbicara persoalan metode tertentu tetapi merupakan hal-hal yang terkait dengan “kondisi-kondisi kemungkinan” yang dengannya seseorang dapat memahami dan menafsirkan sebuah teks, symbol atau prilaku. Lebih jelasnya disini lebih menekankan pad kerangka atau framework dimana sebuah penafsiran didasarkan. Terakhir adalah hermeneutical philosophy atau filsafat hermeneutic yang merupakan bagian dari pemikiran filsafat yang mencoba menjawab problem kehidupan manusia dengan cara menafsirkan apa yang diterima oleh manusia dari sejarah dan tradisi[5]. Dengan keempat tema ini maka hermeneutik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas hakekat, metode dan syarat serta prasyarat penafsiran.
Dalam sejarah perkembangannya, hermeneutika dibagi dalam tiga fase[6]:
1. Dari mitologi Yunani ke teologi Yahudi dan Kristen
2. Dari teologi Kristen yang problematik ke gerakan rasionalisasi dan filsafat
3. Dari hermeneutika filosofis menjadi filsafat hermeneutika
Dari Mitologi Yunani ke Teologi Yahudi dan Kristen[7]
Dalam mitologi Yunani, dewa-dewa dipimpin oleh Zeus bersama Maia.Pasangan ini mempunyai anak bernama Hermes. Hermes inilah yang bertugas untuk menjadi perantara dewa dalam menyampaikan pesan-pesan mereka kepada manusia. Metode hermeneutika secara sederhana merupakan perpindahan fokus penafsiran dari makna literal atau makna bawaan sebuah teks kepada makna lain yang lebih dalam. Dalam artian ini, para pengikut aliran filsafat Antisthenes yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-4 sebelum masehi telah menerapkan hermeneutika pada epik-epik karya Homer (abad IX SM).
Dasar mereka adalah kepercayaan bahwa dibalik perkataan manusia pun sebenarnya ada inspirasi Tuhan. Kepercayaan tersebut sejatinya refleksi pandangan hidup orang-orang Yunani saat itu. Walaupun hermeneutika sudah diterapkan terlebih dahulu, namun istilah hermeneutika pertama kali ditemui dalam karya Plato (429-347 SM). Dalam Definitione Plato dengan jelas menyatakan hermeneutika artinya “menunjukkan sesuatu” dan dalam Timeus Plato mengaitkan hermeneutika dengan otoritas kebenaran. Stoicisme (300 SM) kemudian mengembangkan hermeneutika sebagai ilmu interpretasi alegoris.
Metode alegoris ini dikembangkan lebih lanjut oleh Philo of Alexandria (20 SM-50M), seorang Yahudi yang disebut sebagai Bapak metode alegoris. Ia mengajukan metode bernama typology yang menyatakan bahwa pemahaman makna spiritual teks tidak berasal dari teks itu sendiri, akan tetapi kembali pada sesuatu yang berada di luar teks. Philo menerapkan metode ini atas Kitab Perjanjian Lama, ia menginterpretasikan “pohon kehidupan” sebagai “takut kepada Tuhan”, “pohon pengetahuan” sebagai “hikmah”, “empat sungai yang mengalir di surga” sebagai “empat kebajikan pokok”, “Habil” sebagai “takwa yang bersumber dari akal”, “Qabil” sebagai “egoisme” dan sebagainya. Keempat Hermeneutika alegoris ini kemudian diadapsi dalam Kristen oleh Origen (185-254 M). Ia membagi tingkatan pembaca Bibel menjadi tiga:
a. Mereka yang hanya membaca makna luar teks.
b. Mereka yang mampu mencapai ruh Bibel.
c. Mereka yang mampu membaca secara sempurna dengan kekuatan
spiritual.
Origen juga membagi makna menjadi tiga lapis, yang kemudian dikembangkan oleh Johannes Cassianus (360-430 M) menjadi empat: makna literal atau historis, alegoris, moral dan anagogis atau spiritual. Namun metode ini ditentang oleh gereja yang berpusat di Antioch. Hingga munculnya St. Augustine of Hippo (354-430 M) yang mengenalkan semiotika. Di antara pemikir Kristen lain yang ikut menyumbangkan pemikirannya dalam asimilasi teori hermeneutika dalam teologi Kristen adalah Thomas Aquinas (1225-1274). Sementara itu, Kristen Protestan membentuk sistem interpretasi hermeneutika yang bersesuaian dengan semangat reformasi mereka. Prinsip hermeneutika Protestan berdekatan dengan teori yang digulirkan Aquinas. Di antaranya keyakinan bahwa kehadiran Tuhan pada setiap kata tergantung pada pengamalan yang diwujudkan melalui pemahaman yang disertai keimanan (self interpreting). Protestan juga berpandangan bahwa Bibel saja cukup untuk memahami Tuhan (sola scriptura), di sisi lain, Kristen Katolik dalam Konsili Trent (1545) menolak pandangan ini dan menegaskan dua sumber keimanan dan teologi Kristen, yaitu Bibel dan tradisi Kristen.
2. Dari Teologi Kristen ke Gerakan Rasionalisasi dan Filsafat[8]
Dalam perkembangan selanjutnya, makna hermeneutika bergeser menjadi bagaimana memahami realitas yang terkandung dalam teks kuno seperti Bibel dan bagaimana memahami realitas tersebut untuk diterjemahkan dalam kehidupan sekarang. Satu masalah yang selalu dimunculkan adalah perbedaan antara bahasa teks serta cara berpikir masyarakat kuno dan modern. Dalam hal ini, fungsi hermeneutika berubah dari alat interpretasi Bibel menjadi metode pemahaman teks secara umum. Pencetus gagasan ini adalah seorang pakar filologi Friederich Ast (1778-1841). Ast membagi pemahaman teks menjadi tiga tingkatan:
a. Pemahaman historis, yaitu pemahaman berdasarkan perbandingan satu teks dengan yang lain.
b. Pemahaman ketata-bahasaan, dengan mengacu pada makna kata teks.
c. Pemahaman spiritual, yakni pemahaman yang merujuk pada semangat, mentalitas dan pandangan hidup sang pengarang terlepas dari segala konotasi teologis ataupun psikologis.
Dari pembagian di atas, dapat dicermati bahwa obyek penafsiran tidak dikhususkan pada Bibel saja, akan tetapi semua teks yang dikarang manusia.
3. Dari Hermeneutika Filosofis ke Filsafat Hermeneutika[9]
Pergeseran fundamental lain yang perlu dicatat dalam perkembangan hermeneutika adalah ketika hermeneutika sebagai metodologi pemahaman berubah menjadi filsafat. Perubahan ini dipengaruhi oleh corak berpikir masyarakat modern yang berpangkal pada semangat rasionalisasi. Dalam periode ini, akal menjadi patokan bagi kebenaran yang berakibat pada penolakan hal-hal yang tak dapat dijangkau oleh akal atau metafisika.
Babak baru ini dimulai oleh Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768-1834) yang dianggap sebagai bapak hermeneutika modern dan pendiri Protestan Liberal. Salah satu idenya dalam hermeneutika adalah universal hermeneutic. Dalam gagasannya, teks agama sepatutnya diperlakukan sebagaimana teks-teks lain yang dikarang manusia.
Pemikiran Schleiermacher dikembangkan lebih lanjut oleh Wilhelm Dilthey (1833-1911), seorang filosof yang juga pakar ilmu-ilmu sosial. Setelahnya, kajian hermeneutika berbelok dari perkara metode menjadi ontologi di tangan Martin Heidegger (1889-1976) yang kemudian diteruskan oleh Hans-Georg Gadamer (1900-1998) dan Jurgen Habermas (1929- ).
Pro Kontra Terhadap Hermeneutik
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemunculan hermeneutika dalam kajian al-Qur’an menjadi kontroversial dikalangan umat muslim. Disini penulis akan memaparkan sedikit mengapa sebagian dari kalangan muslim menerima dan menolak hermeneutik dalam mengkaji al-Qur’an.
Ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi kalangan muslim yang menolak hermeneutika sebagai salah satu teori dan metode penafsiran dalam al-Qur’an, diantaranya adalah:
- Berangkat dari sejarah hermeneutika yang berasal dari penafsiran terhadap mitos Yunani, maka hermeneutika dianggap sebagai sebuah desakan rasionalisasi terhadap sebuah mitos yang kemudian hal ini menemukan relevansinya dalam kitab bible yang dianggap sudah tidak otentik bagi kalangan muslim, karena ditulis oleh manusia sehingga jurang perbedaan dan pertentangan yang cukup tajam di dalam teks dapat didamaikan dengan hermeneutik. Bagi penolak hermeneutik hal ini tentu saja berbeda dengan al-Qur’an yang tidak mengalami permasalahan dari segi sejarah karena diyakini sebagai wahyu Tuhan/kalam ilahi dan bukan perkataan Muhammad.
- Hermeneutika dalam hal ini adalah teori interpretasi yang hanya dapat digunakan terhadap teks-teks yang manusiawi. Sedang konsep al-Quran, wahyu dan sejarahnya membuktikan otentisitas bahwa al-Quran lafzhan wa ma‘nan dari Allah Swt. Konsekuensinya, konsep Hermeneutika tidak dapat diterapkan atas al-Quran.
- Tafsir al-Quran yang diterima oleh jumhur selalu bertolak dari arti kosakata bahasa Arab. Al-Quran dan sunnah berbahasa Arab. Tafsir bi al-ra’yi dan alisyârî pun disyaratkan untuk tidak menafikan dan menyimpang jauh dari arti kata yang sebenarnya. Takwil yang dilakukan para ulama pun harus dengan alasan yang menyebabkan sebuah kata tidak dapat diartikan dengan makna aslinya. Dengan nash sebagai titik tolak, al-Quran terhindar dari penafsiran-penafsiran yang liar. Sedang dalam hermeneutika, interpretasi sebuah teks dapat saja berbeda menimbang unsur yang terlibat dalam penafsiran jauh lebih banyak. Perbedaan tempat, waktu dapat menyebabkan perbedaan arti. Belum lagi perbedaan pengetahuan antara penafsir satu dengan lainnya mengenai sisi sejarah teks, psikologis sang pengarang dan sejauh mana kedua faktor tersebut mempengaruhi pemikiran pengarang dalam teks. Sekian faktor tersebut menjadikan hermeneutika lebih bernilai relatif.
- Tafsir dianggap lebih mempunyai pondasi tradisi yang kuat. Sumber primer tafsir dalam Islam adalah al-Quran, Rasulullah Saw. dan sahabat. Tafsir yang berasal dari ketiga sumber tersebut ditransmisikan melalui jalur riwayat yang jelas. Rasulullah Saw menjelaskan arti ayat dengan otoritas yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada para sahabat. Selanjutnya para sahabat mendirikan madrasah-madrasah tafsir sebagai wadah untuk meneruskan rantai riwayat kepada tabi’in. Usai masa tabi’in, muncul upaya untuk mengkodifikasikan tafsir diikuti dengan penetapan syarat-syarat mufassir. Sementara itu bible dianggap bermasalah dengan persoalan otentisitas, sehingga penggunaan hermeneutika dari tradisi Yunani dianggap untuk mempertahankan status Bibel sebagai kitab suci. Tetapi kemudian ketika hermeneutika mulai diterapkan, “kesucian” Bibel justru dibongkar karena dianggap merintangi upaya penafsiran yang ilmiah. Puncaknya terjadi ketika Schleiermacher menyamakan antara teks bibel dan teks Yunani atau Romawi kuno.
Keempat hal diatas yang menyebabkan sebagian kalangan muslim menolak hermeneutika secara mentah-mentah untuk diterapkan dalam metode tafsir al-Qur’an. Ada ketakutan akan hilangnya kesakralan al-Qur’an jika al-Qur’an ditafsirkan secara hermeneutis. Sehingga mereka lebih suka menyukai metode-metode tafsir yang telah dilakukan dan dirumuskan oleh para ulama terdahulu, tanpa bersusah payah membuat metode baru. Disini metode tafsir al-Qur’an yang sudah ada dianggap sudah final dan tidak perlu dikembangkan. Istilah hermeneutik sendiri juga dipermasalahkan karena memang tidak ada dalam kamus arab atau Islam terutama bagi kalangan muslim yang anti barat, sehingga apapun yang berbau barat akan ditolak secara mentah-mentah[10].
Bagi kalangan yang pro terhadap hermeneutik, mereka melihat hermeneutik sebagai jawaban atas keterpurukan umat muslim karena persoalan dan kemunduran yang terjadi dalam masyarakat muslim saat ini persoalan terhadap penafsiran baik terhadap al-Qur’an maupun hadis. Sehingga diperlukan perangkat-perangkat dan metode-metode baru dalam menafsirkan al-Qur’an. Tentu saja hermeneutika tidak akan merubah al-Qur’an atau mendesakralisasi al-Qur’an tetapi justru hal ini akan membawa penyegaran dalam penafsiran al-Qur’an, sehingga al-Qur’an menjadi lebih kontekstual dan bermakna dalam setiap zaman.
Istilah hermeneutika memang tidak dikenal dalam sejarah keilmuan Islam, tetapi sebenarnya praktek hermeneutika telah dilakukan oleh kalangan muslim sejak lama. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Farid Esack dalam bukunya Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur’an, Liberalisme, Pluralism, dimana hal itu dibuktikan, pertama, problematika hermeneutik senantiasa dikaji dan dialami meski tidak dihadapi secara tematis, seperti kajian mengenai asbabun-nuzul dan nasikh mansukh. Kedua, perbedaan antara tafsiran aktual dengan aturan, metode, atau teori interpretasi yang mengaturnya, sudah ada dalam literatur awal tafsir. Ini disistematisasikan dalam prinsip-prinsio tafsir dan ketiga, tafsir tradisional telah di kategorisasi. Beberapa kategori seperti syi’ah, mu’tazilah, ‘Asy’ariyah, dan sebagainya menunjukkan afiliasi ideology, periode, dan aspek historis si penafsir[11].
Namun demikian, meskipun dalam tradisi Islam telah mempraktekkan hermeneutik, tetapi sedikit sekali karya tafsir yang bersifat historis-kritis tentang hubungan antara aspek sosial si penafsir dengan tafsirannya, serta tentang asumsi-asumsi sosiopolitis dan filosofis eksplisit dan implisit yang mendasari kecenderungan teologisnya, hal-hal yang merupakan fokus utama dalam hermeneutika kontemporer[12].
Apa yang telah dijelaskan oleh Farid Esack ini sebenarnya adalah merupakan bantahan bahwa tradisi hermeneutik adalah bukanlah semata-mata merupakan produk keilmuan barat. Meski dalam kenyataanya memang demikian tetapi sebenarnya dalam Islampun akar-akar hermeneutik bukanlah sesuatu yang asing sama sekali karena memang bisa di dapatkan dalam tradisi Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Sehingga penolakan terhadap hermeneutik yang hanya mendasarkan bahwa hermeneutik merupakan metode asing yang coba dipaksakan di dalam kajian al-Qur’an dianggap terlalu berlebihan.
Lebih lanjut ketakutan para penolak hermeneutik yang menganggap penggunaannya (baca hermeneutik) akan menyamakan al-Qur’an dengan teks-teks yang lain termasuk kitab suci agama lain tidak perlu terjadi. Hal ini karena setiap umat beragama memiliki hermeneutika sendiri sebagaimana masing-masing memiliki kitab sucinya sendiri.[13] Sehingga ada hermeneutika al-Qur’an, hermeneutika bible, hermeneutika Upanishad, yang memiliki kekhasan masing-masing yang tidak dimiliki oleh lainnya. Diantara yang berpengaruh dalam penentuan perbedaan antara masing-masing hermeneutika kitab suci adalah hakekat teks atau kitab suci itu sendiri, baik secara historis, teologis, dan linguistik. Dari sini kemudian kitab seci sebagai obyek penafsiran sangatlah menentukan metodologi penafsiran yang dipergunakan. Meskipun metodologi ini ditentukan juga oleh subyek yang menafsirkan tetapi cara pandang subyek terhadap obyek (penafsir terhadap kitab suci), akan sangat berpengaruh terhadap hermeneutika yang diterapkannya.[14] Disinilah kemudian hermeneutika al-Qur’an jelas tidak akan sama dengan hermeneutika bible ataupun hermeneutika teks yang lain, karena al-Qur’an dipandang sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad untuk semua manusia di segala zaman dan bukan hanya eksklusif bagi zaman Muhammad. Al-Qur’an yang ada sekarang ini juga diyakini sama dengan al-Qur’an yang ada pada zaman Nabi. Selain itu bahasa yang digunakan oleh al-Qur’an yakni bahasa Arab dimana penerjemahannya kedalam bahasa lain tetap tidak akan mendapatkan status yang sama dengan al-Qur’an. Hal-hal yang telah disebutkan tersebut tentunya akan membawa hermeneutika al-Qur’an berbeda dengan hermeneutika teks yang lain.
Selain itu hermeneutika dalam penafsiran al-Qur’an ini baru berfungsi setelah Nabi Saw menyampaikan wahyu tersebut. Hermeneutika tidak berurusan dengan sifat hubungan antara Tuhan dan Rasul-Nya dan bagaimana Nabi menerima wahyu tersebut, melainkan dengan kata-kata yang diturunkan dalam sejarah dan disampaikan dari satu manusia kepada manusia lain. Dengan demikian hermeneutika melihat kata-kata tersebut bukan dalam dimensi vertikalnya, tetapi dalam dimensi horizontalnya.[15]
Berbagai Corak Hermeneutika al-Qur’an
Ada satu hal yang cukup mendasar yang membedakan antara hermeneutika dengan metode tafsir sebelumnya, yakni hermeneutika bisa dikatakan bergerak dalam tiga horizon, yakni horizon pengarang, horizon, teks dan horizon penerima atau pembaca atau secara prosedural langkah hermeneutika itu menggarap wilayah teks, konteks, dan kontekstualisi, baik yang berkenaan dengan aspek operasional metodologisnya maupun dimensi epistemologis penafsirannya[16]. Sementara dalam tafsir klasik, wilayah yang dikaji lebih banyak bertumpu pada teks. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, meski embrio pendekatan hermeneutik dalam pemikiran Islam sesungguhnya telah ada, tetapi ruang lingkup cakupan bahasannya masih sangat terbatas pada tradisi keilmuan bayani dan belum sampai masuk terkait dengan tradisi burhani[17].
Setidaknya ada tiga hal yang menjadi asumsi dasar dalam penafsiran al-Qur’an melalui pendekatan hermeneutik, yakni[18]:
- Para penafsir adalah manusia. Siapapun yang menafsirkan teks kitab suci adalah manusia biasa yang terikat oleh ruang dan waktu tertentu, dimana hal ini akan berpengaruh terhadap corak penafsirannya. Dengan asumsi ini maka vonis mutlak akan benar dan salahnya penafsiran diharapkan tidak akan terjadi, sehingga lebih mengarah pada pemahaman dan analisa yang kritis terhadap penafsiran.
- Penafsiran tidak lepas dari bahasa, sejarah dan tradisi. Sehingga pergulatan umat muslim dengan al-Qur’an juga berada dalam “ruang” ini.
- Tidak ada teks yang menjadi wilayah bagi dirinya sendiri.
Dengan tiga asumsi dasar yang dibangun dalam hermeneutika al-Qur’an ini maka hermeneutika diharapkan mampu “kemandegan” dalam keilmuan Islam (baca : ilmu tafsir), yang selama ini dianggap menjadi penyebab kemunduran umat muslim.
Hermeneutika al-Qur’an kontemporer ini diawali dengan munculnya gerakan pembaharuan pada abad ke 18 yang ternyata membawa implikasi pada munculnya suatu penafsiran baru yang diilhami oleh modernitas seperti Ahmad Khan, Amir Ali. Kemudian di Mesir muncul Muhammad Abduh yang menawarkan penafsiran yang bertumpu pada analisis sastra dan sosial. Terma hermeneutika memang belum dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Baru setelah dekade 1960 telah muncul tokoh-tokoh yang serius memikirkan masalah metodologi tafsir. Meskipun kemunculan hermeneutika al-Qur’an ini mulai pada dekade 1960, tetapi kenyataanya baru pada tahun 1970 hermeneutika al-Qur’an mendapat sambutan yang luas tepatnya setelah Fazlur Rahman merumuskan hermeneutika sistematiknya yang dikenal dengan hermeneutika doble movement atau hermeneutika bolak-balik[19]. Metode gerak bolak balik ini secara sederhana dipahami “dari situasi masa kini ke masa al-Qur’an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini”. Gerak yang pertama merupakan tahap pemahaman tekstual al-Qur’an dan konteks sosio-historis ayat-ayatnya dan tahap generalisasi. Gerak pertama disini disebut sebagai tugas pemahaman (task of understanding). Sedangkan pada gerak kedua merupakan perumusan dan realisasi dalam konteks sosio—historis yang konkret di masa sekarang. Dalam gerak kedua ini bukan hanya berkaitan dengan upaya “penubuhan” (embodied) dalam konteks kekinian tetapi juga sebagai “pengoreksi” terhadap hasil-hal atas penafsiran pada gerakan pertama[20]. Metode gerak bolak-balik ini diterapkan Rahman dalam bukunya Tema Pokok al-Qur’an yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat sosial dan kemanusiaan. Sedangkan untuk ayat-ayat eskatologi dia menggunakan metode sintetik-logik.[21]
Kemunculan Rahman yang merumuskan hermeneutika al-Qur’annya menjadi titik tolak bagi perkembangan hermeneutika al-Qur’an kontemporer. Karena meskipun hermeutika al-Qur’an secara sistematik sudah diperkenalkan pada dekade sebelumnya[22] tetapi pada kenyataannya baru mendapatkan sambutan yang luas setelah Rahman merumuskan hermeneutika al-Qur’annya. Lebih lanjut, Fazlur rahman telah menumbuhkan kesadaran baru dilakangan kaum muslimin tentang bagaimana seharusnya menafsirkan al-Qur’an.
Selain Rahman, terdapat juga beragam corak hermeneutika al-Qur’an yang diperkenalkan diantaranya oleh Hassan Hanafi yang dikenal dengan hermeneutika sosial karena lebih berorientasi pada pemecahan problem sosial, hermeneutika pembebasan Farid Esack, karena berorientasi pada pembebasan kaum Muslimin dari penindasan rezim apartheid, serta hermeneutika feminis Amina Wadud Muhsin karena berorientasi pada pembebasan kaum perempuan dari sistem patriarkhis[23]. Berbagai corak hermeneutika al-Qur’an yang lahir ini tentu saja melahirkan bentuk tafsir yang berbeda yang lahir dari perbedaan konteks sosio kultur sang penafsir. Disini penulis tidak akan menjelaskan secara detail perbedaan beragam corak hermeneutika al-Qur’an tetapi yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah bahwa hermeneutika al-Qur’an menawarkan sebuah penafsiran yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pemecahan atas berbagai persoalan umat kekinian. Meski begitu hermeneutika al-Qur’an tidak begitu saja meninggalkan teks-teks al-Qur’an, tetapi hermeneutika justru akan mendialogkan teks-teks al-Qur’an dengan konteks masyarakat saat ini. Dialektika yang terjadi secara terus-menerus ini kemudian akan menampilkan teks yang lebih bermakna sehingga inspirasi al-Qur’an tidak pernah kering sepanjang zaman. Sebaliknya tanpa adanya persentuhan antara teks dan konteks justru teks akan “mati” dan menjadi tidak bermakna.
Signifikansi Hermeneutika dalam diskursus Tafsir al-Qur’an Kontemporer
Bahasa agama (baca al-Qur’an) sebagai representasi bahasa Tuhan bukanlah lahir dalam ruang yang kosong. Hal inilah yang membuat teks-teks al-Qur’an menjadi teks-teks yang bersifat dialogis ketika dibaca, karena memang teks al-Qur’an tersebut memberikan respon terhadap konteks masyarakat arab saat itu. Dalam perkembangannya para pembaca teks al-Qur’an menjadi semakin menemukan “kerumitan” karena jarak, waktu, tempat antara pembaca dengan teks semakin jauh. Teks al-Qur’an yang lahir sekian abad yang lalu di dunia timur tengah kemudian hadir di tengah masyarakat Indonesia kontemporer. Jangankan masyarakat Indonesia yang mempunyai budaya yang jelas-jelas jauh berbeda dengan budaya arab, masyarakat Arab dan Islam secara umum juga menghadapi persoalan yang sama terutama terkait perkembangan dunia dengan berbagai persoalan yang semakin kompleks. Umat muslim seolah tidak berdaya menghadapi perkembangan dunia yang semakin pesat, sehingga bisa dikatakan kondisi umat muslim saat ini menjadi sangat terpuruk diantara dua pilihan terbawa oleh arus zaman atau menghindari pesatnya perkembangan zaman. Hal inilah yang membuat para intelektual muslim seperti Fazlur Rahman, Hassan Hanafi, Farid Esack, Syahroor dan lain sebagainya memberikan tawaran hermeneutik dalam mengkaji al-Qur’an sebagai upaya dalam menjawab tantangan zaman.
Sebagai sebuah teori interpretasi yang kemudian berkembang menjadi sebuah disiplin filsafat, tugas pokok hermeneutika adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau teks yang asing sama sekali menjadi milik kita yang hidup di zaman dan tempat serta suasana kultural yang berbeda. Disini pra konsepsi dan pra disposisi seorang penafsir dalam memahami teks memiliki peran yang besar dalam membangun makna. Selain itu dalam tradisi hermeneutika teks menawarkan berbagai kemungkinan untuk ditafsirkan berdasarkan sudut pandang serta teori yang hendak dipilihnya[24]. Lebih lanjut dalam diskursus hermeneutika kontemporer, orang tidak lagi berbicara tentang salah atau benarnya suatu pendapat karena makna jauh lebih penting daripada kebenaran. Hal ini kemudian -sebagaimana yang dinyatakan oleh Amin Abdullah- dalam wilayah epistemologis, orang sekarang lebih tertarik untuk menerangkan implikasi dan konsekuensi dari sebuah pendapat yang dipegang teguh oleh seseorang atau kelompok bukan soal benar atau salahnya suatu pendapat.[25] Meskipun demikian tidak berarti hermeneutika mendukung paham relativisme-nihilisme, melainkan justru hendak mencari pemahaman yang benar atas sebuah teks yang ada sebagai “tamu asing”. Dengan kata lain hermeneutika berusaha menemukan gambaran dari sebuah bangunan makna yang benar yang terjadi dalam sejarah yang dihadirkan kepada kita oleh teks.[26]
Dengan demikian peran hermeneutika menjadi cukup signifikan dalam penafsiran teks-teks al-Qur’an. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hermeneutika menjadi kunci untuk menjembatani jarak antara teks dengan konteks saat ini sehingga al-Qur’an tidak lagi gagap dalam menjawab tantangan zaman yang dirasakan semakin berat.
Penutup
Demikianlah meski hermeneutika merupakan produk dari keilmuan barat, tetapi kehadiran hermeneutika sebagai sebuah teori interpretasi cukup signifikan dalam mengembangkan penafsiran al-Qur’an. Hal ini karena dalam hermeneutika tidak hanya mempertimbangkan teks tetapi juga konteks dan kontekstualisasi, sehingga dengan menggunakannya teks-teks al-Qur’an menjadi kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman
Daftar Pustaka
Abdullah, Amin, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integratif-Interkonektif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2010.
Esack, Farid, Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur’an, Liberalisme, Pluralisme, Bandung : Mizan, 2000.
Faiz, Fahruddin Teks, Konteks dan Kontekstualisasi (Hermeneutika modern dalam Ilmu Tafsir al-Qur’an Kontemporer), dalam buku Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural, Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50, 2002
Hanafi, Hassan, Muqaddimah fi ‘Ilm al-Istighrab, Kairo: al-Dar al-Fanniyah, 1991.
Hidayat, Komaruddin, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik, Jakarta: Paramadina, 1996.
Kurdi dkk, Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis, Yogyakarta:: Elsaq press, 2010.
Nur Ichwan, Moch, Hermeneutika al-Qur’an: Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir al-Qur’an Kontemporer, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1995
Palmer, Richad E, Hermeneutika : Teori Baru Mengenai Interpretasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Prilakusuma, Angga dalam Telaah Kritis Aplikasi Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Qur’an, dalam http://inzacky.indrawebmaster.com/data_ikpm/Hermeneutika.pdf.
Rahman, Fazlur, Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
——————, Tema Pokok Al-Qur’an, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.
Syamsudin, Sahiron, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
http://www.youtube.com/watch?v=yvxcAka1j8U,
[1] Dalam Islam, nama Hermes sering diidentikkan dengan Nabi Idris, yang dikenal sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan dan mengetahui tulisan, teknologi, astrologi, dan lain-lain. Moch Nur Ihwan, Hermeneutika al-Qur’an: Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir al-Qur’an Kontemporer, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1995, hlm 27
[2] Fahruddin Faiz, Teks, Konteks dan Kontekstualisasi (Hermeneutika modern dalam Ilmu Tafsir al-Qur’an Kontemporer), dalam buku Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural, (Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50, 2002), hlm 41
[3] Ibid., hlm 42
[4] Dr. Phill, Sahiron Syamsudin MA, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm 7
[5] Ibid., hlm 7-10.
[6] Untuk memudahkan dalam memahami sejarah perkembangan hermeneutika disini penulis merujuk pada Hamid Fahmi Zarkasyi yang dikutip oleh Angga Prilakusuma dalam Telaah Kritis Aplikasi Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Qur’an, dalam http://inzacky.indrawebmaster.com/data_ikpm/Hermeneutika.pdf. Pembagian sejarah perkembangan hermeneutik ini agak mirip dengan apa yang ditulis oleh Sahiron Syamsuddin yang membaginya dalam (1) Hermeneurika teks mitos, (2) Hermeneutika teks Bibel dan (3) Hermeneutika umum, lihat Dr. Phill Sahiron Syamsuddin, Ibid., hlm 11. Sementara itu meski mempunyai tujuan yang sama Richad E Palmer mempunyai kategori yang berbeda dalam menjelaskan sejarah perkembangan hermeneutika, dia membaginya dalam enam bentuk yakni (1) Hermeneutika sebagai teori eksegesis bible, (2) Hermeneutika sebagai metodologi filologi, (3) Hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistic, (4) Hermeneutika sebagai fondasi metodologis geisteswessenshaften, (5)Hermeneutika sebagai fenomenologi eksistensi dan pemahaman eksistensial, (6) Hermeneutika sebagai system interpretasi, baik recollektif maupun iconoclastic. Lihat Richad E Palmer, Hermeneutika : Teori Baru Mengenai Interpretasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 38-49
[7] Angga.., Ibid.
[8] Ibid.,
[9] Ibid.,
[10] Di Indonesia, sebagai contoh tokoh yang saat ini cukup tegas dalam menolak penggunaan hermeneutik dengan penafsiran al-Qur’an adalah Adian Husaini, Roem Rowi dan lain sebagaianya. Adian Husaini sering menyatakan betapa bahayanya metode hermeneutika dalam menafsirkan al-Qur’an, dia bahkan menunjuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Syarif hidayatullah Jakarta sebagai “agen barat” yang mempromosikan hermeneutik dan menjadikannya sebagai mata kuliah wajib. Tidak heran jika dalam hal ini orang-orang seperti Amin Abdullah dkk menjadi sasaran kritik tajam dari Adian Husaini. Lihat dalam http://www.youtube.com/watch?v=yvxcAka1j8U,
[11] Farid Esack, Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur’an, Liberalisme, Pluralisme, (Bandung : Mizan, 2000), hlm 94-95
[12] Ibid.,
[13] Pendapat ini juga dikemukakan oleh S.J Samarta sebagaimana yang dikutip oleh Moch NurIkhwan., Op.Cit, hlm 48
[14] Ibid.,
[15] Fahruddin Faiz, Op.Cit hlm 53
[16] Ibid., hlm 44
[17] Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integratif-Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2010), hlm 244-245
[18] Fahruddin Faiz, Op.Cit., hlm 49-50
[19] NurIkhwan, Op.Cit., hlm 42-44
[20] Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm 7-8.
[21] Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur’an, terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm 9-10.
[22] Sebelum Fazlur Rahman, Arkoun telah menawarkan “cara baca” semiotik dalam penafsiran al-Qur’an dan Hassan Hanafi telah mempublikasikan tiga karyanya tentang hermeneutika, yang pertama terkait dengan metode yang digunakan dalam upaya rekonstruksi ilmu usul al-Fiqh, karya keduanya tentang hermeneutika fenomenologis dalam menafsirkan fenomena keagamaan dan keberagamaan dan yang terakhir tekait dengan kajian kritis tehadap hermeneutika eksistensial dalam konteks penafsiran perjanjian baru. NurIkhwan, Op.cit., hlm 44, Lihat juga Hassan Hanafi, Muqaddimah fi ‘Ilm al-Istighrab, (Kairo: al-Dar al-Fanniyah, 1991), hlm 84-86.
[23] Lihat Kurdi dkk, Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis, (Yogyakarta:: Elsaq press, 2010)
[24] Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm 17-18
[25] Amin Abdullah, Op.Cit., hlm 257-258
[26] Komaruddin Hidayat., Op.Cit., hlm 18
1 komentar Januari 23, 2011
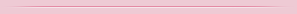
PENDEKATAN ANTROPOLOGIS DALAM PENELITIAN AGAMA (ISLAM) “Sebuah Upaya Peneguhan Relevansi”
Oleh: Syafi’, Yahya, dan Zunly Nadia
A. Belajar dari Jagapura: Sebuah Pengantar[1]
Awal tahun 2009 silam, salah satu penulis sedikit termangu saat mendapatkan tugas untuk membaca al-Qur’an secara estafet di (sekitar) tempat peristirahatan kakek penulis, yang baru saja meninggal dunia. Saat itu penulis mendapatkan putaran waktu keempat, yakni sekitar pukul 22:00 hingga 06:00 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 06:30 WIB pada hari ketujuh, yakni pada saat tim muqaddaman tiba untuk khataman al-Qur’an berikut pembacaan tahlil-nya. Ketermanguan tersebut bukan karena penulis tidak ingin memenjalankannya, melainkan karena munculnya ragam pertanyaan dalam alam pikir penulis, yang mungkin pada saat itu cenderung “liar”.
Pada mulanya, penulis mengira bahwa kegiatan tersebut hanya inisiatif dari bibi penulis, yang notabene cinta dengan al-Qur’an. Beberapa hari sepeninggal kakek penulis, sekelompok orang lain juga terlihat sedang melakukan hal yang sama. Di lain waktu, saat penulis sedang menikmati liburan di kampung halaman, perihal yang sama juga nampak di beberapa makam. Bahkan, suatu hari penulis diminta untuk melakukannya di makam seseorang yang sama sekali tidak penulis kenal dengan tawaran honor bersih Rp. 300.000. Akan tetapi, penulis menolaknya karena dua hari setelahnya harus kembali ke Yogyakarta.
Sesampainya di kota pelajar, penulis mulai sadar bahwa ada tradisi baru yang hidup di masyarakat penulis, yang sekitar 11 tahun sebelumnya tidak pernah penulis jumpai. Saat itu juga penulis melakukan wawancara via Short Massage Sent (SMS) dengan salah satu saudara penulis, yang kebetulan “berprofesi” sebagai pembaca al-Qur’an dalam kegiatan seperti di atas. Dalam diskusi tersebut, penulis bersamanya membincangkan persoalan apakah ritual tersebut dilakukan dalam rangka menahan kedatangan Malaikat Munkar-Mangkir, untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan alam kubur, atau ada persoalan lain yang mendasarinya? Pada saat yang bersamaan, dalam paradigma mereka yang skriptualis tidak ada seruan untuk melakukan hal tersebut. Menurutnya, dengan tegas mengatakan bahwa kegiatan tersebut hanya bersifat ta’abbudi. Namun demikian—dalam pembacaan pendek penulis—ekspresi keberagamaan tersebut tidaklah lahir secara instan. Artinya, ada proses interpretasi panjang terhadap ajaran agama masyarakat setempat yang kemudian terakumulasi menjadi sebuah tradisi. Untuk memahami ritual tersebut, pendekatan etnografis yang bersifat holistik-integratif—yakni model pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan data atas dasar native’s point of view—dan dengan acuan model pendekatan emik—pendekatan yang memandang fenomena sosial budaya atas dasar sudut pandang masyarakat yang menjadi objek kajian,[2] yakni masyarakat Jagapura—barangkali sebagai alternatif pendekatan, di samping juga berbagai pendekatan lain.
Pengalaman sekilas di atas mengindikasikan bahwa studi al-Qur’an maupun hadis dalam bentuk living adalah sebuah keniscayaan yang mesti dirambah oleh para pegiatnya, tanpa meninggalkan juga kajian-kajian yang bersifat teoritis-normatif. Pada saat yang bersamaan, kajian living Qur’an dan living hadis tidak akan mendapatkan hasil maksimal—untuk tidak mengatakan tidak mungkin bisa—jika tidak memanfaatkan pendekatan ilmu-ilmu sosial, termasuk antropologi. Karena demikian, dalam catatan ini penulis bermaksud meneguhkan tentang relevansi pendekatan antropologis dalam penelitian agama. Judul kecil di atas dengan sengaja dibuat karena titik tolak penulis adalah asumsi penerimaan para pembaca atas relevannya pendekatan antropologis dalam penelitian agama. Dalam catatan ini, penulis akan mengawalinya dengan kilasan tentang antropologi, sebagai disiplin ilmu, sebagai sebuah pengantar. Ulasan mengenai relasi agama dan budaya juga akan turut diulas sebagai peneguhan akan relevannya pendekatan antropologis dalam penelitian agama. Sedangkan contoh aplikatifnya penulis deskripsikan secara singkat pada studi al-Qur’an dan hadis melihat pembacanya adalah para pegiat kajian tersebut. Selanjutnya, catatan ini akan ditutup dengan simpulan dan saran untuk para pegiat Qur’anic and prophetic tradition studies dalam memperjelas arah kajian di era kekinian yang lebih kompetitif lagi acap kali berorientasi profit.
B. Antropologi: Ma Huwa, Li Ajli Ma, wa Ma Fih?
Sebelum mendeskripsikan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan antropologi kaitannya dengan penelitian agama, sejarah ringkas tentang antropologi merupakan perihal penting untuk disampaikan dalam catatan ini. Hal ini dilakukan mengingat fakta para pembaca yang beragam dan juga dalam rangka memposisikan maksud antropologi dalam catatan ini. Sehingga, kontroversi terkait dengan antropologi itu sendiri dapat dihindari.
Beberapa kalangan menyebutkan bahwa antropologi[3] muncul pada pertengahan abad XIX, tepatnya sekitat tahun 1860, di mana pada saat itu beberapa karangan yang mengklasifikasikan bahan-bahan mengenai berbagai kebudayaan di dunia dalam berbagai tingkat evolusi. Dalam pada itu, Koentjaraningrat, the father of anthropology di Indonesia, memetakan perkembangan antropologi, yang dalam hemat penulis sangat mudah dipahami, menjadi empat fase, yaitu:[4]
- Sebelum era 1800-an. Fase ini dimulai dengan singgahnya bangsa Eropa di benua Afrika, Asia, dan Amerika sekitar awal abad XVI. Dalam persinggahan tersebut, banyak catatan yang dibuat oleh mereka tentang segala aspek yang berkaitan dengan penduduk setempat, baik berupa adat-istiadat, aneka ragam suku, bentuk fisik, dan lain sebagainya. Berbagai catatan tersebut tersusun secara kabur, tidak teliti, atomistik, dan tidak rapi. Namun demikian, hampir semua catatan tersebut berkelindan pada aspek etnografi. Di kemudian hari, catatan-catatan tersebut diupayakan untuk diintegrasikan dengan penyusunan yang rapi.
- Pertengahan abad XIX. Fase ini dimulai dengan tersusunnya upaya integrasi catatan-catatan pada fase pertama, di mana susunan tersebut didasarkan pada cara berfikir evolusionis. David N. Gellner mengatakan bahwa para antropolog abad ini berfikir bahwa seluruh masyarakat manusia tertata dalam keteraturan, seolah sebagai eskalator historis raksasa, di mana mereka sendiri berada pada posisi puncak, sedangkan masyarakat Eropa dan lainnya yang kurang berkembang berada di tengah. Sementara masyarakat primitif berada di posisi yang paling bawah.[5] Pada fase ini juga muncul karya-karya hasil penelitian yang mengupas persoalan sejarah penyebaran kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa yang juga masih dianggap sebagai sisa-sisa kebudayaan manusia kuno.
- Awal Abad XX. Dalam fase ini antropologi lebih banyak mengamati kebudayaan bangsa di luar Eropa. Hal tersebut terjadi mengingat kolonialisme bangsa Eropa atas non-Eropa semakin memantapkan posisinya. Kondisi demikian menjadikan antropologi sebagai ilmu praktis yang digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial dalam memahami Negara jajahannya.
- Pasca-tahun 1930-an. Sasaran penelitian para antropolog pada era ini beralih ke wilayah penduduk pedesaan, baik secara fisik, masyarakat, maupun kebudayaannya. Pedesaan di sini bersifat umum dalam arti tidak hanya di luar Eropa dan Amerika, di dalam dua benua itu pun juga menjadi bagian dari objek kajianannya.
Bertolak dari empat fase perkembangan tersebut, pada era saat ini corak antropologi di masing-masing wilayah nampak berbeda.[6] Pun juga demikian di Indonesia, dasar-dasar antropologinya hingga sekarang belum ditentukan. Kondisi demikian, menurut Koentjaraningrat justru memberikan ruang kebebasan tersendiri, di mana antropolog dapat memilih ragam corak di atas, dan bahkan mengkombinasikannya sekalipun.[7] Berkaitan dengan itu, penulis memposisikan diri pada antropologi model Meksiko dan India, di mana antropologi didefinisikan sebagai ilmu praktis tentang kemanusiaan yang bersama sosiologi digunakan untuk mengumpulkan data tentang kebudayaan-kebudayaan daerah untuk menemukan dasar-dasar bagi suatu kebudayaan nasional dengan kepribadian yang khas serta dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial-budaya dan merencanakan pembangunan nasional.
Secara garis besar antropologi dapat dipetakan menjadi dua macam, antropologi fisik dan budaya. Antropologi fisik atau biologi merupakan antropologi yang mengkaji manusia sebagai mahkluk biologi. Ia mempelajari manusia dari sudut jasmaniah, dalam arti yang seluas-luasnya. Hal yang diselidiki ialah asal-usul manusia, perkembangan evolusi organik, struktur tubuh dan kelompok manusia yang kita sebut ras.[8] Selain itu, antropologi jenis ini juga mempelajari pengaruh lingkungan terhadap struktur tubuh manusia. Dalam hal ini, lingkungan alam dianggap sangat mempengaruhi ekologi manusia. Sementara itu, antropologi budaya dapat didefinisakan dengan ilmu yang mempelajari kebudayaan pada umumnya dan kebudayaan-kebudayaan dalam berbagai bangsa di seluruh dunia. Ilmu ini menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaanya sepanjang zaman; bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik mampu menciptakan lingkungannya yang tidak diciptakan secara naluriah; dan mengapa suatu bangsa itu cara hidupnya, adat-istiadatnya, sistem kepercayaannya, sistem ekonomi dan hukumnya, keseniannya, sistem moral dan keindahannya, yang dimungkinkan—untuk tidak mengatakan pasti—berbeda antara satu bangsa dengan yang lainnya.[9] Sehingga, cara kerja antropologi budaya adalah mengamati, memahami, dan mendeskripsikan kebudayaan yang terdapat di dalam komunitas manusia. Dari penelitian secara komparatif tentang kebudayaan itu, akhirnya diperoleh sebuah konsepsi tentang kebudayaan manusia pada umumnya, yang merupakan pengertian yang sistematis dan kemudian dapat di gunakan sebagai alat menganalisa masalah kehidupan sosial-kebudayaan manusia.
Selanjutnya, dapatkah agama (Islam) dikaji dengan pendekaatan antropologis, pada saat yang bersamaan ia merupakan produk Tuhan? Sejauh mana relevansi pendekatan antropologis dalam kajian keagamaan? dan bagaimana kerja-kerja oprasionalnya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan diulas dalam dua sub bab selanjutnya sebelum ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran.
C. Membincang Agama dalam Studi Kemanusiaan: Sebuah Keniscayaan
Fenomena agama merupakan fenomena kemanusiaan yang bersifat universal.[10] Meskipun pada tataran sosial acap kali mengalami disorientasi, bukan berarti eksistensi agama dalam masyarakat mengasap tanpa jejak. Universalitas tersebut menunjukkan bahwa kajian tentang manusia atau masyarakat tidak akan lengkap tanpa melihat agama sebagai salah satu elemen. Karena itu, kajian tentang persoalan-persoalan sosial dalam suatu masyarakat yang menafikan aspek agama, sebagai salah satu faktor determinan, tidak akan dapat menggambarkannya secara radikal dan komprehensif.
Sebagai sebuah agama, Islam diyakini berasal dari wahyu yang kemudian diadaptasi dengan kondisi real dalam suatu masyarakat. Adaptasi tersebut nampak sangat jelas dalam praktik ritual keagamaan. Ia merupakan ajaran agama yang disampaikan melalui kitab suci al-Qur’an, yang dalam dataran praktis setiap masyarakat mengaplikasikan ajarannya secara berbeda. Persoalan zakat misalnya, al-Qur’an tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perintah tersebut diaplikasikan. Di era Nabi dan beberapa generasi setelahnya hanya mewajibkan pada aspek pertanian, perdagangan, dan perhiasan, itu pun hanya jenis-jenis tertentu.[11] Berbeda di era sekarang, pada sektor profesi juga merupakan bagian dari harta yang wajib dizakati.[12] Bahkan, dengan melihat transformasi perdaban manusia, konsep zakat klasik, yang lebih membebankan sektor pertanian daripada yang lain, di era sekarang, oleh beberapa kalangan dianggap sudah saatnya harus direkonstruksi.
Perubahan-perubahan demikian mengindikasikan bahwa agama adalah suatu fenomena abadi di satu sisi, dan di sisi yang lain juga memberikan gambaran bahwa keberadaan agama tidak bisa lepas dari pengaruh realitas di sekelilingnya. Keterkaitan tersebut dimungkinkan terjadi karena agama tidak berada dalam realitas yang hampa. Pemahaman demikian sejalan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Atho’ Mudzar tentang bagian Islam yang merupakan produk sejarah.
“Orang dapat berkata, andaikata Islam tidak berhenti di Viena mungkin sejarah Islam di Eropa akan lain. Andaikata Islam terus di Spanyol, sejarahnya lain lagi. Andaikata Islam tidak bergumul dengan budaya Jawa, sejarahnya di Indonesia akan berubah pula. Andaikata Inggris tidak dating ke India, sejarah Islam di anak benua itu akan lain lagi. Demikianlah sebagian wajah Islam di berbagai belahan dunia adalah produk sejarah. Paham muktazilah, kembali kepada pemikiran, sebetulnya juga produk sejarah…. Demikian juga filsafat Islam, kalam, fikih, ushul fikih, juga produk sejarah. Tasawwuf dan akhlak, sebagai ilmu adalah produk sejarah. Akhlak sebagai nilai bersumber dari wahyu, tetapi sebagai ilmu yang disistematisir akhlak adalah produk sejarah.”[13]
Sehingga, bisa dikatakan bahwa mengingkari keterpautan tersebut berarti mengingkari realitas agama sendiri yang selalu berhubungan dengan manusia, yang berada dalam lingkaran budayanya.
Realitas faktual di atas juga mengandung arti bahwa dinamika agama dalam sebuah masyarakat, baik secara doktrinal maupun praktiknya, mengindikasikan adanya campur tangan manusia dalam konstruksinya. Namun demikian, pernyataan ini tidak serta merta berarti bahwa agama merupakan kreasi murni manusia, melainkan dialektika antara kreasi Tuhan, yang tercermin dalam kitab suci, dan konstruksi manusia berupa interpretasi dari nilai-nilai universal agama yang direpresentasikan pada dataran praktis. Interpretasi yang dilakukan tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang melingkar di sekelilingnya. Dengan melihat kenyataan di atas, pernyataan bahwa agama, pada bagian tertentu, merupakan aspek kebudayaan manusia dapat dibenarkan.[14]
Sebagai sesuatu yang inheren dalam kebudayaan manusia tersebut menjadikan realitas keagamaan seseorang (masyarakan) semakin kompleks. Kompleksitas tersebut sebenarnya menandai adanya kompleksitas dalam kehidupan sosial dan budaya, dan bukan agama in it self. Karenanya, kajian terhadap agama pun tidak bisa tidak juga menjadi semakin kompleks, di mana kompleksitas ini sebenarnya menuntut adanya perkembangan dalam studi agama,[15] dan sebagai salah satu kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi kompleksitas ini adalah dibutuhkannya berbagai pendekatan, termasuk di dalamnya adalah pendekatan antropologi.
Sebagai sebuah disiplin ilmu, yang secara sederhana dapat didefinisikan dengan studi tentang manusia (masyarakat) dalam segala perbedaan perilaku, termasuk dirinya sebagai kreator dan produk budaya, [16] antropologi menjadi pendekatan yang sangat signifikan untuk memahami agama (Islam). Dengan pendekatan yang holistik dan komitmen antropologi akan pemahaman tentang manusia, maka sesungguhnya antropologi merupakan ilmu yang penting untuk mempelajari agama (Islam) dan interaksi sosialnya dengan berbagai budaya.[17] Hal ini tidak hanya karena pertemuan keduanya yang telah memunculkan terjadinya perbedaan dalam penafsiran dan praktik keagamaan,[18] tetapi juga karena pergumulannya yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan yang dapat terlihat dari berbagai aspek; baik sosial, ekonomi, maupun politik. Dari sini kemudian pendekatan antropologi dapat menjelaskan mengapa interpretasi terhadap ajaran agama berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.[19]
Dengan demikian, maka sudah barang tentu jika agama yang dipelajari adalah agama sebagai fenomena budaya, bukan ajaran agama sebagai produk Tuhan. Antropologi tidak membahas salah benarnya suatu agama dan segenap perangkatnya, seperti kepercayaan, ritual, dan kepercayaan kepada yang sakral.[20] Wilayah kajian antropologi kaitannya dengan agama hanya terbatas pada kajian terhadap fenomena yang muncul. Dalam konteks keindonesiaan, menurut Atho Mudzhar, ada lima fenomena agama (Islam) yang dapat dikaji, yaitu:[21]
- Scripture atau naskah atau sumber ajaran dan simbol agama;
- Para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yakni sikap, perilaku dan penghayatan para penganutnya;
- Ritus, lembaga dan ibadat, seperti shalat, haji, puasa, perkawinan, dan waris;
- Alat-alat seperti masjid, gereja, lonceng, peci, dan semacamnya;
- Organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul dan berperan, seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Gereja Protestan, Syiah, dan lain-lain.
Kelima obyek di atas dapat dikaji dengan pendekatan antropologi, melihat kelima obyek tersebut memiliki unsur budaya dari hasil pikiran dan kreasi manusia. Namun demikian, peneliti juga harus melihat bagaimana kaitan antara agama dan praktik pertanian, kekeluargaan, politik, magi, dan pengobatan secara bersama-sama. Dengan kata lain, agama tidak bisa diposisikan sebagai sistem otonom yang tidak terpengaruh oleh unsur-unsur sosial lainnya. Inilah ciri dari antropologi modern, yaitu holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalammasyarakat yang sedang diteliti.[22] Memang, beberapa tahun terakhir para penganut dekonstruksi posmodernisme beramai-ramai melakukan serangan terhadap metode tersebut, tetapi bukan berarti akurasi metode tersebut diragukan. Di samping karena sebagaian antropolog tetap mempertahankannya sebagai keputusan metodologis, menurut penulis konstruksi keagamaan masyarakat juga rentan dipengaruhi oleh beberapa faktor di atas.
Kajian tentang agama (Islam) dan budaya di Indonesia tentunya dapat mengembangkan konsep-konsep di atas. Sebab bukan saja Islam di Indonesia menawarkan suatu kekayaan realitas keagamaan, tetapi lebih dari itu, Islam di Indonesia dapat dijadikan model dalam menghadapi dua hal; Pertama, model untuk menjembatani antara budaya lokal dan Islam, mengingat Indonesia terdiri dari beberapa etnis budaya. Perbedaan-perbedaan manifestasi Islam di setiap wilayah akan memberikan model bagi penjelajahan teori. Kedua, Islam lokal di Indonesia mungkin bisa dijadikan model untuk melihat hubungan antara Islam dan dunia modern. Situasi pluralitas budaya Indonesia yang Islam dapat dijadikan suatu model bagaimana negara Islam menerima ide-ide global.
- D. Memahami al-Qur’an dan Hadis dengan Pendekatan Antropologi
Kajian antropologi adalah kajian yang terpusat pada manusia. Selama ini pendekatan antropologi dalam mengkaji agama kerap digunakan dalam mengkaji praktik-praktik keagamaan dalam masyarakat secara empiris, seperti yang dilakukan oleh Clifford Geertz dalam mengkaji secara etnografis masyarakat Jawa, sehingga memunculkan istilah santri, abangan, dan priyayi,[23] Andrew Beatty yang mengkaji agama melalui praktek slametan,[24] dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana pendekatan antropologi jika diaplikasikan dalam studi al-Qur’an dan hadis yang notabene merupakan teks agama (sacred text)?
Al-Qur’an sebagai sebuah teks sakral yang dipercaya sebagai wahyu Tuhan bagi umat muslim dan Hadis sebagai ucapan dan prilaku Muhammad yang dipercaya sebagai Nabi yang menyampaikan wahyu Tuhan bukanlah teks-teks yang lahir dari ruang hampa. Ada kondisi dan situasi yang melingkupi teks-teks tersebut dalam rangka sebuah “dialog” dengan manusia yang menjadi sasaran dari teks tersebut. Dari sini kemudian memahami teks al-Qur’an dan hadis juga meniscayakan akan adanya pemahaman realitas manusia. Sehingga dalam konteks ini pendekatan antropologi menemukan relevansi dan signifikansinya dalam studi al-Qur’an dan hadis.
Pentingnya mempelajari realitas manusia ini juga terlihat dari pesan Al-Qur’an ketika membicarakan konsep-konsep keagamaan. Al-Qur’an seringkali menggunakan “orang” untuk menjelaskan konsep kesalehan. Untuk menjelaskan tentang konsep takwa, misalnya, al-Qur’an menunjuk pada konsep “muttaqien“. Pun juga demikian untuk menjelaskan konsep sabar, misalnya, al-Qur’an menggunakan kata “shabirin”. Merujuk pada pesan al-Qur’an yang demikian itu, sesungguhnya konsep-konsep keagamaan itu termanifestasikan dalam perilaku manusia.[25] Dengan demikian, maka melihat realitas manusia yang ada dalam konteks, di mana al-Qur’an dan hadis disampaikan dengan realitas manusia saat ini, diharapkan akan terlihat pesan universal agama yang senantiasa kontekstual dalam berbagai ruang dan waktu (salih li kull zaman wa makan).
Sementara dalam memahami hadis, perangkat-perangkat keilmuan yang ada selama ini juga menuntut adanya perkembangan lebih lanjut. Karena, perkembangan manusia yang sedemikian cepat membuat ulum al-hadis sudah tidak lagi memadai dalam menyelesaikan persoalan umat saat ini. Ketika menemukan hadis-hadis yang saling bertentangan, misalnya, para ulama hadis kerap menempuh metode tarjih, nasikh-mansukh, al-jam’u, dan/atau tawaqquf. Sikap tawaqquf ini sebenarnya masih bisa diberikan solusi dengan cara memberikan takwil terhadap hadis tersebut.[26] Di samping itu, melalui pendekatan modern—baik antropologi, sosiologi, maupun psikologi—para ulama tidak hanya akan mendapatkan pemahaman yang kontekstual, tetapi juga akan bisa membedakan secara jelas; mana hadis yang mutlak dan terbebas dari ruang waktu, yakni hadis yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, serta mana hadis yang bersifat nisbi, yang terikat oleh ruang dan waktu, yakni hadis yang menyangkut bidang mua’malah, pergaulan hidup, adat-istiadat, yang lebih mencerminkan suatu tradisi atau sunnah yang hidup dalam suatu fase penggal sejarah tertentu.
Selain itu, pendekatan antropologi juga sangat penting dalam meneliti periwayat hadis. Melihat kondisi mikro dan makro seorang periwayat hadis melalui analisa antropologi juga akan sangat membantu dalam menganalisa bagaimana dan mengapa teks-teks hadis tersebut “muncul” apalagi jika hadis-hadis tersebut tidak mempunyai asbabul wurud yang jelas. Hadis tentang larangan wanita pergi sendirian yang berbunyi; “Tidak diperbolehkan seorang perempuan bepergian jauh-jauh kecuali ada seorang mahram bersamanya (HR. Bukhari dan Muslim)“, misalnya, kerap dipahami oleh para ulama sebagai larangan bagi perempuan untuk bepergian yang bersifat sunnah atau mubah, tanpa disertai mahram. Sedangkan untuk bepergian yang bersifat wajib, seperti menunaikan ibadah haji mayoritas ulama hadits menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi perempuan disertai mahram atau suaminya. Hadis ini muncul tanpa adanya asbabul wurud secara khusus. Sehingga, memahami hadis ini seharusnya juga melihat lebih jauh konteks sosio kultur Arab pada masa itu.
Kondisi geografis bangsa Arab memang tidak terlalu “bersahabat”, sebagian besar wilayahnya adalah padang pasir dan hanya ada beberapa daerah yang cukup air dan subur. Selain itu posisi bangsa Arab juga jauh dari pusat-pusat kerajaan besar yang pada saat itu kerajaan yang berkuasa adalah kerajaan Romawi Bizantium di wilayah bagian timur dan kerajaan Persia di wilayah bagian barat, karena memang kondisi alamnya yang cukup sulit untuk dijangkau.
Kondisi bangsa arab yang sedemikian ini tentunya juga cukup bepengaruh terhadap kondisi masyarakatnya yang notabene seolah berada dalam suasana perang, baik perang menghadapi ganasnya alam, perang memperebutkan sumber air sebagai sumber kehidupan, perang antar suku/kabilah karena memang kelangsungan hidup mereka sangat tergantung pada alam. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pembagian peran dalam masyarakat juga sangat tergantung pada kondisi geografis. Laki-laki yang menjalankan peran publik mulai dari mencari nafkah dan mempertahankan keutuhan kabilah, sedangkan perempuan menjalankan peran domestik, seperti mengasuh anak dan mengatur urusan rumah tangga. Selain itu, situasi perang antar suku, di samping melahirkan struktur dan stratifikasi sosial dengan gejala seperti munculnya konsep bangsawan, budak, harem dan Mawali, juga turut mempengaruhinya.
Dari sini, maka bisa dilihat bahwa posisi perempuan memang tidak pernah diperhitungkan pada masa itu. Perempuan adalah salah satu kelompok dalam masyarakat yang hampir tidak pernah menikmati kebebasan hingga kemudian kedatangan Islam di tanah arab yang membawa misi pembebasan.[27] Meskipun kemunculan Muhammad sebagai sang pembawa kebebasan ini membawa perubahan dan angin segar bagi bangsa Arab, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kontinuitas budaya pra-Islam ke dalam Islam masih terjadi dalam berbagai bidang termasuk yang masih terlihat adalah pada struktur keluarga dan ideology patriarkhi.[28] Sebagaimana masyarakat patriarkhi lainnya, perempuan tidak pernah dicantumkan sebagai nama marga (nasab), betapapun hebatnya perempuan itu. Tinggi rendahnya status sosial ditentukan dari pihak bapak (baca: laki-laki). Jika seorang putri bangsawan menikah dengan laki-laki biasa maka status sosial anak-anaknya akan mengikuti bapaknya. Sementara dalam struktur keluarga, peran dominan laki-laki ada dalam berbagai bidang. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai hak utama seperti menjadi wali yang “berhak” menentukan jodoh anaknya, mempunyai hak poligami, jika terbunuh nilai tebusannya lebih besar, dan lain sebagainya. Hal-hal yang demikian tentu mempunyai pengaruh besar dalam ajaran-ajaran agama yang dibawa Nabi Saw.
Hadis tentang larangan bepergian sendirian bagi seorang perempuan tentu mempunyai relevansinya pada masa itu, jika dilihat dari kondisi geografis hingga sosio kultur bangsa Arab. Dalam kondisi gurun pasir, tidak ada otoritas atau kekuasaan polisi, yang ada adalah keamanan yang dijamin oleh kelompok atau kabilah masing-masing, apalagi kendaraan yang ada pada masa itu adalah onta, keledai, dan juga kuda. Jadi, bisa dibayangkan jika kemudian seorang perempuan pergi sendirian mengarungi lautan pasir dengan mengendarai seekor keledai, tentu saja keamanan dan keselamatannya sangat dikhawatirkan. Apalagi nilai yang berlaku pada masa itu adalah tabu jika seorang perempuan pergi sendirian, sehingga akan mencemarkan citranya jika dia bepergian sendirian.
Kondisi demikian tentu sangat berbeda dengan perempuan pada saat ini, di mana perempuan tidak lagi bermasalah dengan persoalan keamanan dan keselamatannya karena adanya sistem keamanan yang telah menjamin keselamatan bagi perempuan. Sehingga, sah-sah saja jika perempuan pergi sendiri untuk berbagai macam tujuan termasuk dalam menuntut ilmu, bekerja, dan lain sebagainya. Dengan demikian mahram tidak lagi dipahami sebagai person tetapi juga dipahami sebagai sistem keamanan yang menjamin keselamatan bagi kaum perempuan.
Ini merupakan contoh sederhana dari sebuah pendekatan antropologi dalam memahami hadis, yang tentu saja juga tidak dapat dilepaskan dari pendekatan lain, yakni pendekatan historis dan pendekatan sosiologi. Pendekatan antropologi dalam hal ini adalah memperhatikan pola-pola perilaku pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia.[29] Di sini, antropologi ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi. Sedangkan pendekatan historis menekankan pada alasan mengapa Nabi Saw bersabda dilihat dari konteks sosio-kultur bahkan politik masyarakat masa itu. Sementara pendekatan sosiologi lebih menyoroti pada posisi manusia yang membawanya kepada suatu prilaku.[30] Dengan memahami teks-teks bagi al-Qur’an maupun hadis melalui berbagai pendekatan, diharapkan muncul sebuah pemahaman baru yang lebih apresiatif terhadap perkembangan zaman tanpa harus kehilangan semangat dan nilai yang terkandung dalam teks-teks tersebut.
- E. Penutup
Simpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah bahwa meskipun agama sebuah entitas yang bukan semata-mata produk manusia, namun bukan berarti tidak bisa didekati dengan antropologi. Sebaliknya, penggunaan pendekatan tersebut sangat relevan guna melihat sejauh mana kandungan nilai, ragam aplikasi, dan perihal lain yang berkelindan dalam unsur-unsur keagamaan itu sendiri. Bahkan, pembacaan sebuah kebudayaan suatu masyarakat tidak akan radikal-komprehensif tanpa melihat sistem agama (keyakinan) yang ada di dalamnya, karena prilaku seseorang dan/atau masyarakat kerap dipengaruhi oleh konstruksi paham keagamaannya. Terlebih jika melihat agama di Indonesia yang secara mayoritas adalah sinkretis, sudah barang tentu pendekatan antropologi adalah sebuah keniscayaan, di samping juga membutuhkan pendekatan-pendekatan lain, seperti sosiologis, historis, psikologis, feminis, dan lain sebagainya.
Wa Allah A’lam bi al-Shawab
BAHAN BACAAN
Abdullah, Amin (dkk.). Metode Penelitian Agama. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim. Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
Abdurrahman, Dudung. Sosial-Humaniora dan Sains dalam Studi Keislaman. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
Beatty, Andrew. Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account. United Kingdong: Cambridge University Press, 1999.
Connolly, Peter (ed.). Aneka Pendekatan dalam Studi Agama. Terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS, 2002.
Geertz, Clifford. Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia. USA: The University of Chicago Press, 1971.
____________. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.
____________. Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Terj. Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto. Jakarta: Pustaka Jaya, 1982.
Harsoyo. Pengantar Antropologi. Ttt: Bina Cipta, tt.
Honko, Iauri (ed.). Science of Religion: Studies and Methodology. Ttt: Mouton Publishers, 1979.
Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
_____________. Pengantar Antropologi: Pokok-pokok Etnografi. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Saefudin, Ahmad Fedyani. Antropologi Kontemporer. Jakarta: prenada Media Grup, 2006.
Morris, Brian. Anthropological Studies of Religion: An Introductory Text. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
Mudzar, M. Atho’. Pendekatan Studi Islam: dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Munawwar, Said Agil Husein al-. “Metode Pemahaman Hadis; Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis”, dalam Jurnal Metafora. Jakarta: HMJ TH Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah , 1998.
Olson, Carl (ed.). Theory and Method in the Study of Religion: A Selection of Critical Readings. Ontario: Nelson Thomson Learning, 2003.
Sujono, Pendekatan Studi Agama dalam Kajian Islam, dalam http://ahmadsamantho.wordpress.com/2008/03/22/antropologi-agama/. Diakses pada tanggal 23 Desember 2010.
Tibi, Bassam. Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an. Jakarta: Paramadina, 1999.
Zahwu, Abu. Al-Hadis wa al-Muhadditsun. Mesir: Syirkah Mishriyyah, tt.
[1]Jagapura merupakan nama dari sebuah kampung pelosok yang secara teritorial berada di perbatasan Cirebon-Indramayu bagian tengah (2 KM. arah selatan dari pangkalan migas Mundu, Indramayu). Secara administratif ia termasuk dalam wilayah kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saat ini, kampung Jagapura dibagi menjadi empat wilayah; Jagapura Kidul, Jagapura Lor, Jagapura Wetan, dan Jagapura Kulon. Umumnya, keislaman masyarakat Jagapura beraliran sunni yang bertradisikan Nahdlatul Ulama konservatif. Mata pencahariaan utama masyarakatnya adalah sektor pertanian. Kedekatannya dengan Ibu Kota Jakarta sedikit banyak mempengaruhi transformasi perekonomian masyarakat Jagapura secara perlahan ke sektor perdagangan dan buruh, meski belum sampai menandingi sektor pertanian.
[2]Baca, James P. Spradley, Metode Etnografi (Yogyakarta: Tiara wacana, 1997), hlm. 35-76.
[3]Term antropologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani yang berupa; antrhos (manusia) dan logos (ilmu). Sehingga, secara harfiah ia dapat dimaknai dengan ilmu tentang manusia.
[4]Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 2-4.
[5]David N. Gellner, “Pendekatan Antropologis”, dalam Peter Connolly (ed.), Aneka Pendekatan dalam Studi Agama, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 15-16.
[6]Telusuri perbedaan corak tersebut dalam Koentjaraningrat, op. Cit., hlm. 5-6.
[7]Ibid., hlm. 6-7.
[8]Yang termasuk dalam kategori ini adalah; Palaenontologi, yaitu ilmu yang mempelajari deskripsi dari varitas manusia yang telah tidak ada lagi dan makhluk lain yang masih erat hubungannya denga manusia; Evolusi manusia, yaitu ilmu yang mempelajari proses perkembangan dari tipe-tipe manusia duimulai dari makluk-makluk bukan manusia; Antropometri, yaitu studi tentang teknik pengukuran tubuh manusia; Somatologi, yaitu studi tentang varietas manuisa yang masih hidup dan tentangperbedaan sex dan variasi perseorangan; Antropologi rasial, ilmu yang mempelajari penggolongan manusia dalam kelompok-klompok ras, sejarah ras manusia dan hal-hal tentang percampuran ras, dan lain sebagainya. Harsoyo, Pengantar Antropologi (Ttt: Bina Cipta, tt), hlm.15-16.
[9]Yang termasuk dalam kategori ini adalah; Arkeologi Prasejarah, adalah ilmu yang mempelajari perkembangan kebudayaan manusia di masa lampau ketika belum dapat bahan-bahan tertulis. Cara kerja penelitian antropologi ini tidak berdasarkan pada bahan-bahan tertulis, maka penelitiannya menggunakn bahan-bahan peninggalan materiil yang berupa artefak atau fosil-fosil; Antropologi Linguistik; antropologi linguistik ini digunaklan sebagai penelitian terhadap timbulnya bahasa dan bagaimana terjadinya variasi dalam bahasa-bahasa selama jangka waktu selama berabad-abad. Selain itu, juga merupakan bagian dari kajian mengenai bahasa, akan tetapi khususnya yang terkait dengan keaneka ragamannya. Wilayah kajian ini lebih kecil dibandingkan dengan kajian linguistik secara umum, karena antropologi linguistik memang hanya memfokuskan diri pada kaitannya dengan antropologi, bukan pada semua bahasa; Etnologi, adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia dengan mengadakan pendekatan perbandingan dari kebudayaan-kebudayaan secara individual yang terdapat di muka bumi ini. Etnologi meneliti secara teoritis masalah-masalah persamaan dan perbedaan yang ada antara kebudayaan-kebudayaan setelah diadakan perbandingan; Kebudayaan dan Kepribadian, cabang antropologi ini bertujuan untuk mencari penjelasan terhadap kebutuhan, keinginna, perangsang dan implus-implus serta tingkah laku yang beraneka ragam yang dijalankan orang untuk mencapai kepuasan sosial kultural dan sosial-psikologis. Masalah-masalah yang yang dikemukakan oleh antropologi ini adalah sejahuh mana individu dapat melepaskan diri atau keluar dari batas-batas tradisi dan kebiasaan kebudayaannya dan dengan jalan apakah masyarakat itu membentuk kepribadian anggota-anggotanya. Harsoyo, Pengantar Antropologi…, hlm. 19-23, lihat pula, Yayasan Obor Indonesia, Pokok-pokok Antropologi Budaya, terj. Yasan Obor Indonesia, (Jakarta: Yasan Obor Indonesia, 1996), hlm.10, dan Ahmad Fedyani Saefudin, Antropologi Kontemporer (Jakarta: prenada Media Grup, 2006), hlm. 21
[10]Max Muller, sebagaimana dikutip Brian Morris, mengakui bahwa suatu keyakinan terhadap Tuhan merupakan hal yang universal di kalangan manusia dan bersamaan dengan bahasa ia membentuk dasar identitas etnik. Brian Morris, Anthropological Studies of Religion: An Introductory Text (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), hlm. 93.
[11]Lihat, Abu Yahya Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab bi Syarkh Minhaj al-Thullab (Surabaya: al-Hidayah, tt), juz I, hlm. 102-113. Periksa juga beberapa hadis yang menjadi landasan konstruksi tersebut dalam, Hasan Sulaiman al-Nuri dan Alawi Abbas al-Maliki, Ibanat al-Ahkam: Syarkh Bulugh al-Maram (Beirut: dar al-Fikr, 2004), juz II, hlm. 213-248.
[12]Jenis zakat ini diposisikan sama dengan sektor perdagangan. Sebab, berprofesi sama halnya dengan menjual jasa. Contoh yang sederhana adalah profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
[13]M. Atho’ Mudzar, Pendekatan Studi Islam: dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 23.
[14]C. Kluckhohn, sebagaimana dikutip Koentjaraningrat, dalam karyanya, Universal Categories of Culture (1953), mengidentifikasi bahwa terdapat tujuh unsur-unsur pembentuk suatu kebudayaan manusia, yaitu; bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencahariaan hidup, sistem religi, dan kesenian. Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi…, hlm. 80-81. Lihat juga kerangka gambar Koentjaraningrat berikut penjelasannya pada halaman 92-94. Baca juga penjelasan Clifford Geertz tentang agama sebagai sebuah sistem kebudayaan dalam, Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), hlm. 87-125.
[15]Dalam hal ini menarik apa yang diungkapkan oleh Ibrahim Moosa ketika memberikan kata pengantar dalam buku Fazlur Rahman, Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism, yakni sebagai berikut:… “Having raised the question of international relations, politics and economics, that does not mean that scholars of religion must become economics and political scientists. However, the study of religion will suffer if its insights do not take coqnizance of how the discources of politics, economics, and culture impact on the performance of religion and vice-verse”. Ebrahem Moosa “Introduction” dalam Fazlur Rahman, Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism, (Oxford:Oneworld Publication, 2000), hlm 28
[16]Carl Olson, “Antropology”, dalam Carl Olson (ed.), Theory and Method in the Study of Religion: A Selection of Critical Readings (Ontario: Nelson Thomson Learning, 2003), hlm. 238.
[17]Sujono, Pendekatan Studi Agama dalam Kajian Islam, dalam http://ahmadsamantho.wordpress.com/2008/03/22/antropologi-agama/. Diakses pada tanggal 23 Desember 2010.
[18]Karena pada saat manusia melakukan interpretasi terhadap ajaran agama, maka mereka dipengaruhi oleh lingkungan budaya―primordial―yang telah melekat di dalam dirinya.
[19][1]Pendekatan antropologi dalam kajian komparatif Islam di Indonesia dan Maroko yang dilakukan oleh Clifford Geertz, misalnya, membuktikan adanya pengaruh budaya dalam memahami Islam. Di Indonesia Islam menjelma menjadi suatu agama yang sinkretik, sementara di Maroko Islam mempunyai sifat yang agresif dan penuh gairah. Perbedaan manifestasi agama itu menunjukkan betapa realitas agama sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya. Lihat, Clifford Geertz, Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia (USA: The University of Chicago Press, 1971).
[20]M. Atho’ Mudzar, op. Cit., hlm. 15.
[21]Ibid., hlm. 60.
[22]David N. Gellner, op. Cit., hlm. 34.
[23]Lihat, Clifford Geertz, Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto (Jakarta: Pustaka Jaya, 1982).
[24]Lihat, Andrew Beatty, Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account, (United Kingdong: Cambridge University Press, 1999).
[25]Sujono, loc. Cit.
[26]Orang yang pertama kali berbicara mengenai ta’wil al-hadis adalah Imam Syafi’i. Lihat, Abu Zahwu, Al-Hadis wa al-Muhadditsun (Mesir: Syirkah Mishriyyah, tt), hlm 471. Lihat juga, Said Agil Husein al-Munawwar, “Metode Pemahaman Hadis; Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis”, dalam Jurnal Metafora (Jakarta: HMJ TH Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah , 1998), hlm 33.
[27]Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 104-107.
[28]Kontinuitas nilai dalam masyarakat merupakan hal yang wajar, karena setiap kelompok masyarakat tidak bisa bebas dari nilai-nilai lokal dan nilai universal. Kalau beberapa institusi keagamaan pra-Islam di dalam Islam diakomodir di dalam Islam, bukan berarti hal ini adalah kelanjutan dari agama-agama selanjutnya tanpa pesan-pesan baru, tetapi konsep universalitas dalam ajaran Islam antara lain dibangun atas nilai-nilai lokal yang boleh jadi bersumber dari agama-agama sebelumnya. Ibid.
[29]Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm 1.
[30]Said Agil Husein Al-Munawwar…, op. Cit, hlm. 34-35.
1 komentar Desember 31, 2010
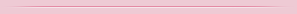
Pentingnya Penataan Angkringan dan Warung Lesehan dalam Mengembangkan Wisata Kuliner di kota Yogyakarta
Yogyakarta memang menyimpan sejuta potensi wisata yang cukup kaya dan beragam. Mulai dari wisata alam seperti pantai parangtritis dan gunung merapi, hingga wisata budaya seperti kraton, candi dan khazanah seni budaya lainnya dapat dengan mudah kita jumpai di Jogja. Karenanya, tak heran bila banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan utama wisata mereka setelah Bali.
Setiap wisatawan yang datang dan singgah di Yogyakarta, tentunya bukan sekedar bertujuan untuk melihat-lihat keindahan alam dan keunikan budaya Jogja, melainkan lebih dari itu mereka juga pasti penasaran dan ingin mencicipi masakan khas yang ada di Yogyakarta.
Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Yogyakarta menyimpan banyak sekali makanan tradisional seperti “jadah ketan tempe bacem”, “sego abang lombok ijo” , ronde, bajigur, bahkan model tempat makan seperti “warung angkringan” dan “warung lesehan”, yang menurut kita yang tinggal di Yogyakarta ini nampak “biasa-biasa” saja menjadi daya tarik tersendiri yang tidak sedikit membuat orang luar Jogja penasaran untuk mencicipinya.
Oleh sebab itu, perlu kiranya kita menggali kembali khazanah kuliner Jogja yang sebenarnya begitu kaya itu untuk kemudian “dikelola” sehingga layak “jual” bagi wisatawan. Karena bila kita bisa mengemas potensi kuliner dengan baik dan menarik, bukan tidak mustahil justru khazanah kuliner itulah yang akhirnya menjadi daya tarik utama para wisatawan untuk datang ke Jogja.
Mengembangkan potensi wisata kuliner menjadi semakin penting karena dalam beberapa tahun belakangan ini muncul kecenderungan kuat di kalangan kelas menengah dan masyarakat urban yang menjadikan makan bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan biologis untuk mengisi perut yang lapar, melainkan makan telah berubah fungsi menjadi gaya hidup yang didalamnya terdapat relasi-relasi sosial, ekonomi dan budaya yang saling berkaitan. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang harus pergi keluar kota atau minimal ke luar rumah hanya untuk mencari makan atau rumah makan. Sebuah keluarga yang tinggal di Bantul, misalkan, tidak jarang setiap hari minggu memiliki agenda makan siang besama di sebuah rumah makan yang terletak di Jalan Kaliurang. Padahal bisa saja keluarga itu memasak sendiri untuk dimakan bersama keluarganya begitu juga sebaliknya. Tapi karena makan telah menjadi kebutuhan sosial berupa jalan-jalan di hari libur bersama keluarga, maka mereka lalu memilih makan bersama di luar rumah.
Budaya angkringan dan warung lesehan sebenarnya menjadi salah satu aset wisata kuliner yang selama masih diremehkan. Angkringan dan warung lesehan seringkali dianggap sebagai tempat murahan yang hanya mengotori pemandangan kota Yogyakarta. Padahal jika keduanya di tata dengan sedemikian rupa, akan menjadi tempat tujuan wisata kuliner bagi para penikmat makanan tradisional. Karena tujuan dari wisata kuliner tidak hanya sekedar ingin merasakan makanan khas daerah, tetapi lebih dari itu wisata kuliner seharusnya juga dipadukan dengan tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini misalnya, angkringan. Angkringan adalah suatu model warung kaki lima yang hanya ada di kota Yogyakarta dan Solo, dan jarang kita mendapatinya di kota lain. Inilah yang sebenarnya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung kota Yogyakarta. Mereka akan merasakan budaya makan di angkringan dan lesehan yang mungkin jarang di temui terlebih oleh wisatawan dari mancanegara. Sehingga jika angkringan ditata dan dikemas sedemikian rupa akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Add a comment Desember 29, 2010
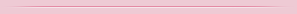
JENIS-JENIS KITAB HADIS
Kitab-kitab Hadis terbagi ke dalam berbagai macam bentuk dan jenis yang berbeda-beda sesuai tujuan dan fungsi disusunnya kitab tersebut. Berikut ini jenis-jenis kitab Hadis yang banyak digunakan oleh umat Islam.
1) Kitab Jami’ atau Jawami’
Penulisan kitab Jami` bermaksud menghimpunkan Hadis-hadis berkenaan dengan bidang aqidah, ahkam, riqaq, adab, tafsir, tarikh dan sirah, fitan dan manaqib.
Kitab Hadis Sahih Bukhari merupakan salah satu kitab yang digelar kitab Jami’ (atau Jawami’) . Untuk disebut sebuah kitab Hadis sebagai Jami’ sebuah kitab hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya delapan bidang .
- Aqaid (akidah): Contohnya: Kitab al-Tauhid karangan Abu Bakar Ibn Abi Khuzaimah, Kitab al-Asma wa al-Sifat oleh al-Baihaqi
- Ahkam: Kitab Hadis hukum yang disusun seperti dalam kitab-kitab fiqh seperti Bulugh maram dan Umdatul ahkam.
- Riqaq ( raqaaiq) : dinamakan juga sebagai Ilmu al-Suluk wa al-Zuhd iaitu menyebut tentang peringatan di hari akhirat dan azab kubur yang akan melembutkan hati sesiapa yang mendengarnya dan menjadikannya seorang yang zuhud.
Contohnya: Kitab Zuhud oleh Abdullah Ibn Mubarak, Imam Ahmad.
- Adab: Adab sopan, adab tidur, adab solat, adab makan dan sebagainya. Contohnya kitab al-Adab al-Mufrad oleh al-Bukhari dan Kitab Syamail oleh Tirmizi
- Tafsir: Hadis-hadis yang mentafsirkan al-Quran.
Contohnya kitab Tafsir ibn Mardawaih, ibn Jarir at-Tabari, Tafsir al-Dailami dan Tafsir Jailani. - Tarikh: Sejarah terbagi kepada dua jenis:
a- Sejarah tentang kejadian alam ( bada’ al-khalq) seperti kejadian langit dan bumi, syurga, neraka, jin, syaitan, malaikat dan sebagainya
b- Sejarah tentang kehidupan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat seperti Sirah Ibn Hisyam, Sirah Mulla Umar,dan sebagainya.
- al-Fitan yaitu fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman bermula selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. Contohnya, kitab Muin bin Hammad (guru al-Bukhari) tentang Dajjal, turunnya nabi Isa as, kemunculan Imam Mahdi, dan sebagainya. Beliau telah mencampuradukkan antara yang sahih dan tidak sahih.
- Manaqib (tentang kelebihan seseorang seperti Abu Bakar,Umar,Uthman,dan Ali, tabi’in, ahlul bait, isteri-isteri Rasulullah s.a.w., Nawasib dan sebagainya) contohnya, al-Riyadh al-Nadhirah Fi Manaqib al-`Asyarah oleh Muhib al-Tabari, Zakhair al-`Uqba Fi Manaqib Zawi al-Qurba dan lain-lain.
Antara kitab-kitab Hadis yang termasuk dalam kategori ini ialah Sahih al-Bukhari Jami’ al-Tirmizi, Sahih Muslim, Misykat al-Masabih, Jami` Suyfan al-Thauri, Jami` Abdul Razzaq bin Hammam al-San`ani, Jami’ al-Darimi, dan lain-lain.
2) al-Sunan dan al-Ahkam
Kitab Hadis yang disusun mengikuti tertib fiqh yang bermula dengan bab Taharah, sembahyang dan seterusnya. Walaubagaimanapun di dalam kitab sunan sendiri tidak hanya memuat tentang hukum-hukum normative, tetapi ada juga perkara-perkara lain yang dibincangkan.
Contoh kitab-kitab yang termasuk dalam kategori ini ialah: Sunan al-Nasai’e, Jami` al-Tarmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Daruqutni, Sunan Abi Ali bin al-Sakan dan lain-lain.
3- Masanid dan Musnad
Kitab Hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan Hadis. Biasanya dimulai dengan nama shabat yang pertama kali masuk Islam atau menyesuaikan dengan urutan abjad.
Imam Ahmad yang menulis musnad telah mendahulukan Hadis-hadis Abu Bakar daripada Hadis-hadis sahabat yang lain.
Di antara cara penyusunan musnad adalah:
- memuat Hadis-hadis tentang 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga, atau tentang khalifah yang empat.
- mengurutkan siapa yang lebih dahulu yang memeluk Islam.
- dengan melihat siapakah ahli Badar/ Hudaibiah dahulu.
- dengan melihat siapakah yang memeluk Islam terlebih dahulu ketika Pembukaan Mekah.
- dengan melihat lelaki dahulu perlu diutamakan. Tetapi dari kalangan wanita pula isteri-isteri nabi diutamakan terlebih dahulu.
- atau dengan melihat jenis qabilah (qabilah bani Hasyim didahulukan).
Di dalam musnad jumlah Hadis tidak dibatasi jumlahnya. Ia cuma mengumpulkan sebanyak mungkin Hadis-hadis yang menerangkan tentang sesuatu perkara. Namun begitu musnad yang paling sahih adalah Musnad Ahmad kerana beliau telah menyaring Hadis-hadisnya. Kebanyakan ulama salaf menulis Hadis-hadis dalam bentuk musnad.
4- Ma’ajim dan mu’jam
Mu’jam disusun mengikut tertib huruf ejaan, atau mengikut susunan nama guru-guru mereka. Nama guru-guru mereka juga disusun mengikut ejaan nama atau laqob mereka.
Mu’jam juga hanya mengumpulkan Hadis-hadis nabi s.a.w tanpa melihat kwalitas Hadis-hadisnya.
Contoh kitab-kitab mu’jam ialah Mu’jam Tabrani, Mu’jam kabir, Mu’jam as-Sayuti, dan Mu’jam as-Saghrir, Mu’jam Abi Bakr, ibn Mubarak, dan sebagainya.
Kitab rijal yang mengumpulkan orang-orang yang tersebut dalam meriwayatkan Hadis-hadis nabi s.a.w. mengikiut ejaan bersama dengan kuniyyahnya. Ini semua adalah untuk memastikan kesahihan sesebuah Hadis.
5- Masyikhat
Di dalam penulisan masyikhat, Hadis-hadis dikumpul dari seorang syeikh yang mana syekh yang bersangkutan mengumpulkan sendiri Hadis tersebut atau orang lain yang mengumpulkannya. Contohnya, Masyikhat Ibn al-Bukhari, yang dibuat tambahan oleh Hafiz al-Mizzi, Masyikhah Ibn Syadam al-Kubra dan al-Sughra, dan dibuat tambahan oleh al-`Iraqi. Ali bin Anjab al-Baghdadi mempunyai 20 jilid kitab masyikhat. Antara kitab Masyikhat yang disebutkan juga ma’ajim seperti Mu’jam al-Sayuti, Abu Bakar Ibn Mubarak. Kitab yang ada sanad pula seperti Musnad al-Firdaus oleh al-Dailami.
Istilah lain bagi mu’jam dengan makna kamus dan bukannya bermaksud penulisan Hadis. Ada juga yang menyebut mu’jam itu sebagai kamus geografi yang menyebut tentang geografi sesuatu tempat seperti Mu`jam al-Buldan oleh Yaqut al-Hamawi. Ada juga yang mengumpulkan tentang biografi seseorang tokoh di dalam kitab mu’jamnya seperti al-Mu`jam fi Athar Muluk al-`Ajam.
6- Ajza’/ Rasail
Hadis-hadis yang dikumpulkan berdasarkan suatu perkara tertentu atau tema tertentu seperti Raf` al-Yadaian oleh al-Bukhari. Dalam kitab ini beliau mengemukakan Hadis-hadis tentang mengangkat tangan tanpa membahaskan kedudukan Hadis-hadis tersebut apakah ada yang mansukh, syaz, atau mujmal dan sebagainya. Contoh-contoh lain seperti Juz al-Niyyah oleh Ibn Abi al-Dunya, Juz al-Qira’ah Khalf al-Imam oleh al-Baihaqi, Juz Fadhail Ahl al-Bait oleh Abu al-Husin al-Bazzar, Juz al-Munziri Fi Man Ghufira Lah Ma Taqaddama Min Zanbih, Juz Asma al-Mudallisin dan Juz `Amal al-Yaum wa al-Lail.
Tujuan kitab Rasail ini ditulis adalah:
1- Untuk membuktikan sesuatu perkara itu sabit (mendapat ketetapan) daripada Rasulullah s.a.w dengan mengumpulkan pelbagai riwayat tanpa mengira kedudukan Hadis-hadis tersebut.
2- Supaya lebih mudah untuk membuat kajian terhadap sesuatu perkara.
7- Arbainat
Kitab-kitab Hadis yang mengumpulkan Hadis sebanyak 40 buah Hadis. Usaha ini dilakukan berpandukan Hadis riwayat dari Abu al-Darda’ yang disebut oleh al-Baihaqi: “Sesiapa yang hafal untuk ummatku 40 Hadis berhubung urusan agamanya, Allah akan bangkitkannya nanti sebagai seorang faqih dan aku (Muhammad) pada hari kiamat nanti akan menjadi syafaat kepadanya”. Imam Ahmad berkata, Hadis ni masyhur tetapi tidak sabit.
Abdullah bin Mubarak adalah orang pertama yang menulis kitab arbainat ini.
Ibn Hajar pula telah menulis 2 kitab Arbain. Kitab Arba`inat yang paling mashyur ialah karangan al-Nawawi. Antara syarahnya pula ialah Syarah Ibn Rajab, Syarah Mulla Ali al-Qari dan lain-lain.
Ada juga ulama yang mengumpul Hadis 40 berkenaan tauhid, mensabitkan sifat-sifat Allah, Hadis hukum, Hadis-hadis yang sanadnya semua sahih, mengumpulkan Hadis-hadis yang mempunya lafaz panjang, mengumpul Hadis-hadis yang mengambil Hadis-hadis tersebut dari 40 tokoh ulama atau 40 orang sahabat. Ada juga Hadis-hadis yang ditulis mengikuti keturunan yang sama, dan ada juga kumpulan Hadis yang sanadnya hanya ‘daripada Malik daripada Nafi` daripada Ibn Umar’ saja.
8- Afrad dan Ghara’ib
Penulisan tentang Hadis-hadis yang hanya terdapat pada seorang syaikh tetapi tidak ada pada syaikh yang lain. Tegasnya Hadis-hadis yang mempunyai seorang perawi saja. Fard nisbi atau fard mutlak (seorang sahaja yang meriwayatkannya dari sahabat).
9- Mustadrak
Kitab Hadis yang mengumpulkan Hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh seseorang pengarang sebelumnya secara sengaja atau tidak. Contohnya kitab Mustadarak al-Hakim setebal 4 jilid di mana Hadis-hadis tersebut dikumpul menepati syarat-syarat yang digunakan oleh Bukhari dan Muslim.
Kitab ini tidak boleh dibaca begitu saja, tetapi mesti bersama dengan takhrijnya oleh al-Zahabi. Antara contoh kitab-kitab mustadrak yang lain adalah seperti Mustadrak Hafiz Ahmad al-Maliki. Tujuan penyusunan kitab Mustadarak ialah: Supaya kita tidak menganggap Hadis sahih hanyalah apa yang terkandung di dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim sahaja.
10- Mustakhraj
Mengumpulkan Hadis-hadis yang sama dalam satu kitab tetapi sanadnya berlainan di mana sanadnya bertemu dengan syeikh kitab asalnya (gurunya) seperti Hadis tentang niat.
Contoh kitab Mustakhraj ialah Mustakhraj Abu ‘Awanah `Ala Sahih Muslim.
Ada juga yang hanya membawa Hadis-hadis tersebut tetapi tidak membawa sanadnya. Beliau cuma menyebut kitab-kitab yang menyebut tentang perawinya. Tujuannya adalah: Supaya Hadis-hadis tersebut akan lebih meyakinkan dengan banyaknya para perawi yang meriwayatkan Hadis tersebut.
Contoh lain juga ialah Mustakhraj ala Sahihain:
1) Mustakhraj atas kitab Sahih Muslim oleh Abu Ja`far bin Hamdan, Abu Bakar al-Jauzaqi, Abi Imran Musa bin Abbas, Abi Said bin Utsman dan sebagainya.
2) Mustkhraj ke atas Bukhari saja seperti karangan al-Ismaili, Abu Abdillah dan lain-lain.
3) Mustakhraj ke atas Bukhari dan Muslim pula seperti Mustakhraj oleh Abi Abdillah, Abi Muhammad al-Khallan, Abi Bakar al-Siraji, dan sebagainya.
Ada juga Mustakhraj atas al-Tirmizi oleh Abi Ali al-Tusi, Mustakhraj atas Abu Daud, Kitab al-Tauhid karangan Ibn Khuzaimah. Bagaimanapun mereka tidak beriltizam tentang kesahihannya.
Ada juga yang mentakrifkan Mustakhraj yang mana sanadnya bertemu dengan tabi`in tetapi ada iktilaf mengenainya. Faedah penyusunan kitab Mustakhraj:
1-Ketinggian sanad- ia ditulis untuk menunjukkan sanadnya lebih tinggi dari kitab asal seperti Muslim. Contoh Abu `Awanah dalam kitabnya Mustakhraj Abu ‘Awanah yang mengambil sanad Hadis tersebut atas lagi daripada guru Muslim.
2-Menunjukkan kekuatan Hadis itu. Contohnya jika Hadis itu hanya disebutkan di dalam Sunan Abu Daud saja, tetapi tidak diriwayatkan oleh orang lain. Sekiranya Hadis tersebut terdapat dalam Sunan Abu Daud itu pula bertentangan dengan Hadis yang lain, maka ia perlukan penguat. Dengan adanya kitab Mustakhraj, kita dapat mencari penguat-penguatnya yang lain supaya proses pentarjihan dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, kitab Mustakhraj penting sebagai penguat apabila riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat.
3-Menerangkan sanad yang tidak jelas. Contohnya pada peringkat permulaan seseorang perawi itu masih kuat ingatannya tetapi semasa menghampiri akhir hayatnya ia menjadi seorang yang mukhtalit (nyanyuk). Dengan itu dapat dipastikan bilakah sebuah Hadis itu diambil sama dengan ketika ingatannya masih kuat atau selepas menjadi nyanyuk. Contohnya perawi Bukhari dan Muslim, Hisyam bin Urwah bin Zubair yang nyanyuk selepas berhijrah ke Iraq.
4-Kitab asal riwayat dari mudallis yang dikira daif sekiranya menggunakan lafaz ‘an. tetapi dengan adanya Mustakhraj, adanya sanad lain yang mengunakan lafaz yang menunjukkan dengan jelas yang dia mendengar Hadis.
5-Riwayat secara mubham– yaitu perawi yang tidak dijelaskan namanya seperti ‘haddatsana rajulun min ahli bait’. Tidak diketahui siapa ‘rajulun’ itu? Nama perawi mubham akan diketahui apabila memeriksa kitab Mustakhraj.
6-Mengetahui siapakah orang yang disebut namanya secara muhmal tanpa kunyahnya-contoh Muhammad. Muhammad yang mana?
7-Isnad asal ada `illah yang sukar untuk diselesaikan tanpa berpandukan kepada riwayat yang bebas `illah. Contohnya perawi tersebut dituduh sebagai Syiah, Irja’dan sebagainya.
11-`Ilal
Sebuah kitab yang menyebut tentang kecacatan pada sebuah periwayatan Hadis, baik dari segi matannya atau sanadnya. Contohnya kitab al`Ilal karangan Ibn al-Jawzi dan Muhammad Abu Hatim al-Razi yang mengikuti susunan bab-bab fiqh.
12-Atraf
Sebuah Kitab yang menyebut sebagian dari Hadis dari sisi permulaannya saja, di tengah-tengahnya, atau diakhir saja. Hal ini banyak dilakukan terutama oleh Bukhari untuk mengeluarkan sesuatu hukum dari sebuah Hadis. Ada juga Atraf Sunan Abi Daud, Jami’ al-Tirmizi dan Sunan al-Nasa’i dan sebagainya. Ibn Hajar al-Asqalani juga ada mengarang kitab yang berjudul Ithaf al-Mahara Bi Atraf al-`Asyarah yang mengumpulkan 10 buah kitab Hadis di dalamnya berserta sanadnya yaitu:
1-al-Muwatta’
2-Musnad Ahmad
3-Musnad al-Syafi`e
4-Sahih Ibn Khuzaimah
5-Mustadrak al-Hakim
6-Sunan al-Daruqutni
7-Jami’ al-Darimi
8- Muntaqa Ibn al-Jarud
9-Sahih Ibn Hibban
10-Mustakhraj Abi Awanah
Pada dasarnya, penulisan hadis itu baru dimulai pada abad ke 2 Hijriyah. Pada masa Nabi masih hidup, penulisan Hadis dilarang keras oleh Nabi karena khawatir akan bercampur dengan al-Qur’an dan berpotensi dipalsukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan islam saat itu. Nabi pernah bersabda “Jangan kamu tuliskan sesuatu yang telah kamu terima dariku selain al-Qur’an. Barang siapa menuliskan yang ia terima dariku selain al-Qur’an hendaklah ia hapus. Ceritakan saja yang kamu terima dariku, tidak apa-apa. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya di neraka”. (HR.Muslim). Hadis di atas jelas sekali melarang siapapun untuk menuliskan sesuatu yang keluar dari mulut Rasul kecuali al-Qur’an.
Akan tetapi zaman terus berjalan dan jumlah kaum muslim semakin banyak dan banyak pula yang sudah mengenal al-Qur’an. Dengan demikian hukum menulis Hadis akhirnya diperbolehkan dengan pertimbangan perlunya mendokumentasikan sabda-sabda Nabi yang bisa dijadikan pegangan bagi umat islam dalam menjalankan agamanya. Sejak saat itu, maka dikenallah dua orang sahabat Nabi yang selalu menulis apa-apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Nabi, dua orang sahabat itu Abdullah bin Amr bin Ash dan Jabir bin Abdullah al-Anshary. Tulisan-tulisan Abdullah dikenal dengan “Ashahifah As-Shadiqah” dan tulisan-tulisan Jabir dikenal dengan “Shahifah Jabir”.
Setelah umat islam semakin tersebar ke sejumlah penjuru dan tidak sedikit di anatara para sahabat penghafal hadis yang meninggal, maka dilakukanlah sebuah proyek pembukuan Hadis pada abad ke 2 Hijriyah, yaitu tepatnya pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di antara kitab-kitab yang mashur pada abad ke 2 Hijriyah ini adalah Kitab al-Muwatta’ yang disusun oleh Imam Malik pada tahun 144 H. Selain itu, Musnad Assyafi’I dan Mukhtaliful Hadis karya Imam Syafi’I juga menjadi kitab yang masyhur pada abad ini. sedangkan pada abad ke 3 Hijriyah kita mengenal kitab-kitab Hadis karya Muhammad bin Isma’il al-bukhary dengan nama kitabnya yang terkenal “Shahih Bukhary” atau Jami’us Shahih dan Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy dengan karya terkenalnya “Shahih Muslim”. Selain kedua kitab tersebut, pada abad ke 3 Hijriyah ini juga lahir kitab-kitab Hadis terkenal lainnya seperti Sunan Abi Daud, Sunan At-Turmudzy, Sunan an-Nasa’I, dan Sunan Ibnu Majah.
Kalau pada abad pertama, kedua dan ketiga Hadis berturut-turut mengalami masa periwayatan, penulisan dan penyaringan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in, maka di abad ke 4 ini para ulama hadis sudah melakukan penyelidikan terhadap hadis-hadis dan kitab-kitabnya yang telah disusun oleh ulama abad sebelumnya. Di abad ke 4 ini kitab-kitab yang lahir adalah seperti Mu’jamul Kabir, Mu’jamul Aushat, Mu’jamus Saghir (ketiganya karya Imam Sulaiman bin Ahmad At-Thabarany w.360 H). Selain itu, kitab-kitab seperti Sunan ad-Daraqhutny karya Imam Abul Hasan Ali bin Umar bin ahmad ad-Daraqhutny juga lahir pada abad ini. Tentunya masih banyak lagi kitab-kitab yang lahir pada abad ini, namun karena keterbatasan ruang maka tidak bisa disebutkan semuanya.
Sedangkan untuk abad ke 5 Hijriyah, para ulama ahli Hadis sudah melakukan pengklasifikasian Hadis-hadis sesuai dengan tema-tema tertentu ke dalam satu kitab Hadis. Selain itu, ulama abad ini juga melakukan pensyarahan (menguraikan dengan luas) dan mengikhtisarkan (meringkas) kitab-kitab Hadis yang telah disusun pada abad-abad sebelumnya. Kitab-kitab Hadis yang lahir pada abad ini adalah seperti “Sunannul kubro” karya Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaky, kitab “Muntaqa’l Akhbar” karya Majdudin Al-Harrany, kitab “Nailul Authar” karya Muhammad bin Ali As-Saukany, dan sebagianya.
Selanjutnya bangkit ulama ahli Hadis yang berusaha menciptakan kamus Hadis untuk mencari pentakhrij suatu Hadis atau untuk mengetahui dari kitab hadis apa suatu hadis didapatkan. Kitab yang berbicara tentang itu misalkan: “Al-Jami’us Shagir fi Ahadisil Basyiri’n Nadzir” karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada juga kitab “Al-Mu’jamul Mufahras lil Al-Fadhil Hadis Nabawy” karya Dr.A.J.Winsinc dan Dr.J.F. Mencing, kedua adalah dosen bahasa Arab di Universitas leiden, Belanda. Dan tentunya masih banyak lagi kitab-kitab Hadis yang lainnya yang ditulis pada abad ke 5 dan seterusnya itu. Karena keterbatasan ruang, maka tidak mungkin bisa disebut satu persatu. Namun yang jelas, perkembangan penulisan kitab Hadis tidak pernah berhenti dan justru terus mengalami perkembangan dan kemajuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.
( Sekian )
Bahan Bacaan
Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis, Bandung, PT. Al-Ma’arif, 1995
Yunahar Ilyas, M. Mas’udi (ed), Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis, Yogyakarta, LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam) UMY, 1996.
Jalaluddin Rakhmat, Pemahaman Hadis: Perpektif Historis, Bandung, Jurnal Al-Hikmah No.17, Vol VII, 1996.
1 komentar Desember 29, 2010
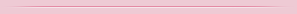
SEPUTAR ILMU HADIS
Dalam hirarkis sumber ajaran Islam, posisi Hadis menempati urutan ke dua setelah al-Qur’an. Posisi hadis yang seperti itu karena fungsinya sebagai tibyanan atau penjelas bagi hal-hal yang memang belum dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur’an. Sebagaimana kita ketahui, bahwa al-Qur’an adalah firman Allah yang masih bersifat global. Pesan-pesan dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh al-Qur’an masih sangat umum dan tidak merinci secara praktis. Karena itu, dibutuhkan sebuah penjelas atau perinci terhadap yang umum itu sehingga mudah dipahami oleh umat Islam. Nah, merinci dan menjelaskan keglobalan al-Qur’an itulah yang dilakukan oleh Hadis.
Sedangkan dalam struktur hukum Islam, posisi Hadis juga tidak kalah urgennya dengan al-Qur’an. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Artinya, bila suatu masalah itu tidak bisa ditemukan dalil-dalilnya dalam al-Qur’an, maka hendaklah dicarinya di dalam Hadis. Sebagaimana dalam firman Allah: “Ta’atlah engkau kepada Allah dan kepada Rasulmu dan kepada Ulil Amri (pemimpinmu)….”. Ayat ini bermakna bahwa kita harus merujuk pada al-Qur’an dalam menyelesaikan masalah, akan tetapi bila dalam al-Qur’an tidak ada, maka merujuklah kepada Hadis Rasul, dan bila dalam Hadis Rasul tidak ada, maka mintalah pertimbangan kepada pimpinanmu.
Melihat posisi Hadis yang begitu penting seperti di atas, maka urgensi mempelajarai Hadis sebenarnya sama urgennya dengan mepelajari al-Qur’an. Selain alasan-alasan yang menyangkut keistimewaan posisi Hadis di atas, sebenarnya ada alasan-alasan yang tak kalah pentingnya kenapa kita perlu mempelajari Hadis. Alasan-alasan itu adalah menyangkut orisinalitas sebuah hadis. Berbeda dengan al-Qur’an yang sudah dijaga keasliannya oleh Allah, maka Hadis sebenarnya berpotensi mengalami pemalsuan. Karena itu, problem yang selalu muncul dan senantiasa menjadi perdebatan dalam ilmu hadis adalah menyangkut orisinalitas. Problem orisinalitas ini sebenarnya hendak mempertanyakan apakah sebuah hadis itu benar-benar bersumber dari Nabi atau tidak? Karena itu, dalam ilmu Hadis pasti akan ditemukan sebuah metode yang disebut dengan kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad adalah untuk menguji ketersambungan sanad sebuah hadis beserta kualifikasi-kualifikasi para perawynya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menguji keaslian sebuah materi hadis (matan hadis) apakah ia benar-benar bersumber dari nabi atau tidak.
Dengan demikian, di antara alasan yang paling pokok dari urgensi mempelajari ilmu Hadis adalah karena hadis itu statusnya bermacam-macam; ada yang shahih, hasan dan dha’if.. Dan di antara bermacam-macam hadis itu tidak semuanya bisa dijadikan sumber ajaran Islam apalagi sumber hukum Islam. Suatu contoh, Hadis-hadis Dha’if, menurut sebagian besar Ulama, tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Ia hanya bisa dijadikan sebagai rujukan bagi perilaku-perilaku keseharian kita yang tidak terkait dengan hukum. Seperti keutaman makan, tidur, berjalan, dan sebagainya. Yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum hanyalah hadis yang benar-benar berstatus shahih dan bersumber dari Nabi Muhammad. Persoalan-persoalan seperti inilah yang kerap kali tidak banyak diketahui oleh umat Islam, sehingga tidak sedikit Hadis dha’if yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan Hadis Shahih tidak dijadikan sebagai rujukan apapaun.
Hal lainnya yang menjadi alasan kenapa kita penting mempelajari ilmu Hadis adalah karena sebagian Hadis ada yang memiliki asbabul wurud (sebab-sebab turunnya Hadis). Secara fungsional Asbabul wurud Hadis berguna untuk: 1). Menolong dalam memahami dan menafsirkan pesan-pesan yang terkandung dalam Hadis. Karena sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu itu merupakan sarana untuk mengetahui musabbab (akibat) yang ditimbulkannya. Seseorang tidak mungkin mengetahui penafsiran suatu Hadis secara tepat tanpa mengetahui sebab-sebab dan keterangan-keterangan tentang latar belakang suatu Hadis yang bersangkutan. 2). Untuk mengetahui hikmah-hikmah ditetapkannya sebuah syariah hukum. Dan 3). Untuk mentakhsiskan (merinci) suatu hukum yang bisa jadi bersifat global dalam sebuah Hadis.
Oleh sebab itu, urgensi mempelajari ilmu Hadis semakin relevan karena ternyata dalam sebuah Hadis itu terdapat berbagai macam problem yang tidak sederhana. Kalau kita coba sederhanakan, alasan-alasan yang mendorong kita perlu mempelajari ilmu Hadis itu adalah karena:
-
- Hadis sebagai sumber pedoman kedua dalam agama Islam setelah al-Qur’an
- Hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an
- Terdapat berbagai macam jenis Hadis Dha’if yang perlu kita hindari untuk digunakan sebagai sumber hukum Islam.
- Potensi pemalsuan terhadap Hadis cukup besar
- Proses periwayatan sebuah Hadis melalui waktu yang panjang dan melibatkan banyak perawy sehingga kita perlu menyelidiki mana Hadis yang betul-betul Sahih
- Ada Hadis-hadis tertentu yang memiliki Asbabul Wurud
Keenam alasan di atas adalah sejumlah alasan kenapa kita perlu mempelajari ilmu Hadis. Namun demikian, keenam alasan di atas bisa jadi akan mengalami perkembang sesuai kebutuhan orang yang hendak mempelajari ilmu Hadis. karena sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam mempelajari ilmu Hadis itu terdapat berbagai macam cabang ilmunya. Namun secara garis besar, ilmu Hadis itu terbagi dua, yaitu, ilmu Hadis riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah.
Ilmu Hadis Riwayah adalah suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara periwayatan, pemeliharaan dan pembukuan Hadis Nabi. Sedangkan ilmu Hadis Dirayah adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui hal-ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan Hadis, sifat-sifat Rawi dan lain sebagainya. Jadi, obyek ilmu Hadis riwayah adalah bagaimana sebuah Hadis itu diterima dan disampaikan kepada orang lain. Terlepas matannya Hadis itu ada yang janggal atau beri’llat, itu bukan wilayah kajian ilmu Hadis riwayah. Sementara itu, obyek kajian ilmu Hadis dirayah adalah meneliti kelakuan para rawy dan keadaan marwynya (sanad dan matannya). Manfaat ilmu ini adalah untuk menetapkan maqbul (diterima) atau mardud (ditolaknya) suatu Hadis sehingga benar-benar bisa diamalkan.
Kedua ilmu di atas secara metodologis masih bersifat umum. Selain kedua ilmu tersebut masih ada cabang-cabang ilmu lainnya yang secara khusus mempelajari aspek-aspek tertentu dalam ilmu Hadis. Misalkan ilmu-ilmu yang berfokus pada sanad seperti:
- Ilmu Rijalil Hadis yaitu ilmu pengetahuan yang dalam pembahasannya membicarakan hal ihwal dan sejarah kehidupan para rawy dari golongan sahabat, tabi’in, dan tabi’it tabi’in. Ilmu Rijalil Hadis sendiri terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu:
- Ilmu Tawarihi’r Ruwah yaitu ilmu yang membahas tentang kapan dan dimana seorang rawy dilahirkan dan dari siapa dia menerima Hadis, siapa yang pernah mengambil Hadis darinya, serta kapan dan dimana dia itu wafat.
- Ilmu Jarh wa Ta’dil adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang caranya memberikan kritikan terhadap Aib seorang rawy dan cara memberikan pujian bagi keunggulan rawy.
-
- Ilmu Thabaqatir Ruwah, yaitu ilmu yang membahas tentang pengelompokan para rawy ke dalam suatu angakatan atau generasi tertentu.
- Ilmu Mu’talif wal Mukhtalif, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang persamaan bentuk tulisan dari nama asli, nama samaran, dan nama keturunan para rawy, namun bunyi bacaannya berlainan.
- Ilmu Muttafiq wal Muftariq, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang persamaan bentuk tulisan dan bunyi bacaannya akan tetapi berlainan orangnya.
- Ilmu almubhamat yaitu suatu ilmu yang membahas nama-nama rawy yang tidak disebut dengan jelas.
Ilmu-ilmu yang berpangkal pada matan seperti:
- Ilmu Gharibil Hadis ialah ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafadz-lafadz dalam matan Hadis yang sulit dan sukar difahami karena jarang sekali digunakannya.
- Ilmu Asbabi Wurudil Hadis ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang sebab-sebab turunnya sebuah Hadis.
- Ilmu Tarikhil Mutun. Bila asbabul wurud itu titik beratnya membahas latar belakang dan sebab-sebab lahirnya Hadis, maka tarikhil mutun ini menitik beratkan pembahasannya kepada kapan atau di waktu apa Hadis itu diucapkan atau perbuatan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
- Ilmu Nasikh wa Mansukh ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang Hadis yang datang belakangan sebagai penghapus terhadap ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan Hadis yang datang sebelumnya.
- Ilmu Mukhtaliful Hadis yaitu ilmu yang membahas Hadis-hadis yang secara lahir nampak bertentangan dengan Hadis yang lainnya, padahal sebenarnya kalau mau diteliti tidak ada pertentangan di dalamnya. Yang menjadi obyek ilmu ini adalah Hadis-hadis yang nampak berlawanan untuk kemudian dikompromikan kandungannya, baik dengan cara membatasi (taqyid) kemutlakannya maupun dengan mengkhususkan (takhsis) keumumannya dan lain sebagainya.
Sedangkan ilmu yang berfokus pada sanad dan matan sekaligus adalah: Ilmu ‘Ilalil Hadis yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang membahas sebab-sebab yang samar-samar serta tersembunyi dari segi membuat kecacatan sebuah Hadis. Seperti memuttashilkan (mengganggap bersambung) sanad suatu hadis yang sebenarnya sanad itu mungkhati’ (terputus), merafa’kan (mengangkat sampai ke Nabi) berita atau kabar yang mauquf (yang hanya sampai kepada sahabat), menyisipkan suatu Hadis pada Hadis yang lain, serta meruwetkan sanad dengan matannya atau sebaliknya.
Sejumlah cabang ilmu di atas adalah alat yang dibuat ulama (muhaddisin) untuk mempelajari Hadis Nabi pada saat masa hidup ulama dahulu. Kini, para ulama kontemporer sudah banyak juga yang melengkapi ilmu Hadis dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masa kini. Para ulama masa kini tidak segan-segan memakai pendekatan sosiologi, antropologi, sejarah, linguistik, hermeneutika, politik dan sebagainya dalam mempelajari Hadis Nabi. Pendekatan politik misalkan berusaha menelusuri apakah seorang rawy itu pernah terlibat pada urusan politik atau tidak. Karena bila ia pernah terlibat dengan politik, maka bisa jadi Hadis-hadis yang diriwayatkannya ada yang bermuatan politis sehingga diragukan orisinalitasnya. Pendekatan politik ini nampaknya penting karena para sahabat yang nota bene banyak meriwayatkan Hadis itu juga tidak sedikit yang pernah menjadi panglima atau gubernur pada masa itu. Sehingga kepentingan-kepentingan politiknya dikhawatirkan akan terbawa dalam meriwayatkan sebuah Hadis.
Begitu pula dengan pendekatan sejarah juga amat penting untuk memahami konteks sejarah sosial budaya pada saat munculnya Hadis. Sejarah di sini adalah sejarah Nabi (sirah Nabawiyah) dan sejarah kebudayaan Arab pada masa lalu. Dengan mengetahui sejarah kebudayaan Arab masa lalu, kita bisa mengkaitkan sebuah Hadis dengan peristiwa-peristiwa atau kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. Misalkan tentang Jilbab. Jilbab sebanarnya adalah budaya masyarakat Arab yang sudah ada sejak lama. Ketika Islam datang, jilbab lalu diwajibkan oleh Islam untuk dipakai oleh perempuan muslim sehingga seolah-olah jilbab itu hanya keputusan Islam saja. Dengan mengetahui sejarah dan kebudayaan Arab pada saat itu kita bisa memahami dan memposisikan bahwa jilbab adalah bagian dari budaya Arab yang dilestarikan oleh agama Islam sehingga kini lebih dikenal sebagai pakaian muslim.
Beberapa pendekatan kontemporer dalam mempelajari Hadis Nabi di atas biasanya dipadu dengan pendekatan klasik dalam ilmu Hadis. Misalkan pendekatan asbabul wurud dipadukan dengan pendekatan sejarah kebudayaan Arab sehingga Hadis yang kita teliti benar-benar bisa diandalkan orisinalitasnya. Begitu pula dengan ilmu rijalil Hadis bisa dipadukan dengan pendekatan politik dalam melihat para erawy Hadis sehingga kredibilitas seorang perawy betul-betul bisa diketahui secara sempurna.
Selain kita mempelajari hal ihwal tentang sanad dan matan Hadis, kita juga perlu mempelajari kitab-kitab Hadis yang tersebar ke dalam ribuan kitab Hadis. Mungkin kitab hadis yang kita kenal selama ini hanyalah kitab Shahih Bukhori dan Kitab Shahih Muslim. Padahal, terdapat ribuan kitab hadis yang dikarang oleh ribuan ahli Hadis (muhaddisin) dari berbagai negara dan masa.
Add a comment Desember 29, 2010
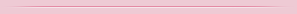
PEMBAGIAN HADITS
Dilihat dari konsekuensi hukumnya:
- Hadits Maqbul (diterima): terdiri dari Hadits shahih dan Hadits Hasan
- Hadits Mardud (ditolak): yaitu Hadits dha’if
Penjelasan:
HADITS SHAHIH:
Yaitu Hadits yang memenuhi 5 syarat berikut ini:
- Sanadnya bersambung (telah mendengar/bertemu antara para perawi).
- Melalui penukilan dari perawi-perawi yang adil.Perawi yang adil adalah perawi yang muslim, baligh (dapat memahami perkataan dan menjawab pertanyaan), berakal, terhindar dari sebab-sebab kefasikan dan rusaknya kehormatan (contoh-contoh kefasikan dan rusaknya kehormatan adalah seperti melakukan kemaksiatan dan bid’ah, termasuk diantaranya merokok, mencukur jenggot, dan bermain musik).
- Tsiqah (yaitu hapalannya kuat).
- Tidak ada syadz. Syadz adalah seorang perawi yang tsiqah menyelisihi perawi yang lebih tsiqah darinya.
- Tidak ada illat atau kecacatan dalam Hadits
Hukum Hadits shahih: dapat diamalkan dan dijadikan hujjah.
HADITS HASAN:
Yaitu Hadits yang apabila perawi-perawinya yang hanya sampai pada tingkatan shaduq (tingkatannya berada di bawah tsiqah).
Shaduq: tingkat kesalahannya 50: 50 atau di bawah 60% tingkat ke tsiqahannya. Shaduq bisa terjadi pada seorang perawi atau keseluruhan perawi pada rantai sanad.
Para ulama dahulu meneliti tingkat ketsiqahan seorang perawi adalah dengan memberikan ujian, yaitu disuruh membawakan 100 hadits berikut sanad-sanadnya. Jika sang perawi mampu menyebutkan lebih dari 60 hadits (60%) dengan benar maka sang perawi dianggap tsiqah.
Hukum Hadits Hasan: dapat diamalkan dan dijadikan hujjah.
HADITS HASAN SHAHIH
Penyebutan istilah Hadits hasan shahih sering disebutkan oleh imam Tirmidzi. Hadits hasan shahih dapat dimaknai dengan 2 pengertian:
- Imam Tirmidzi mengatakannya karena Hadits tersebut memiliki 2 rantai sanad/lebih. Sebagian sanad hasan dan sebagian lainnya shahih, maka jadilah dia Hadits hasan shahih.
- Jika hanya ada 1 sanad, Hadits tersebut hasan menurut sebagian ulama dan shahih oleh ulama yang lainnya.
HADITS MUTTAFAQQUN ‘ALAIHI
Yaitu Hadits yang sepakat dikeluarkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim pada kitab shahih mereka masing-masing.
TINGKATAN HADITS SHAHIH
- Hadits muttafaqqun ‘alaihi
- Hadits shahih yang dikeluarkan oleh imam Bukhari saja
- Hadits shahih yang dikeluarkan oleh imam Muslim saja
- Hadits yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, serta tidak dicantumkan pada kitab-kitab shahih mereka.
- Hadits yang sesuai dengan syarat Bukhari
- Hadits yang sesuai dengan syarat Muslim
- Hadits yang tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim
Syarat Bukhari dan Muslim: perawi-perawi yang dipakai adalah perawi-perawi Bukhari dan Muslim dalam shahih mereka.
HADITS DHA’IF
Hadits yang tidak memenuhi salah satu/lebih syarat Hadits shahih dan Hasan.
Hukum Hadits dha’if: tidak dapat diamalkan dan tidak boleh meriwayatkan Hadits dha’if kecuali dengan menyebutkan kedudukan Hadits tersebut. Hadits dha’if berbeda dengan hadits palsu atau hadits maudhu`. Hadits dha’if itu masih punya sanad kepada Rasulullah SAW, namun di beberapa rawi ada dha`f atau kelemahan. Kelemahan ini tidak terkait dengan pemalsuan hadits, tetapi lebih kepada sifat yang dimiliki seorang rawi dalam masalah dhabit atau al-`adalah. Mungkin sudah sering lupa atau ada akhlaqnya yang kurang etis di tengah masyarakatnya. Sama sekali tidak ada kaitan dengan upaya memalsukan atau mengarang hadits.
Yang harus dibuang jauh-jauh adalah hadits maudhu`, hadits mungkar atau matruk. Dimana hadits itu sama sekali memang tidak punya sanad sama sekali kepada Rasulullah saw. Walau yang paling lemah sekalipun. Inilah yang harus dibuang jauh-jauh. Sedangkan kalau baru dha`if, tentu masih ada jalur sanadnya meski tidak kuat. Maka istilah yang digunakan adalah dha`if atau lemah. Meski lemah tapi masih ada jalur sanadnya.
Karena itulah para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan hadits dha`if, dimana sebagian membolehkan untuk fadha`ilul a`mal. Dan sebagian lagi memang tidak menerimanya. Namun menurut iman An-Nawawi dalam mukaddimahnya, bolehnya menggunakan hadits-hadits dha’if dalam fadailul a’mal sudah merupakan kesepakatan para ulama.
Untuk tahap lanjut tentang ilmu hadits, silakan merujuk pada kitab “Mushthalahul Hadits”
Buat kita orang-orang yang awam dengan ulumul hadits, tentu untuk mengetahui derajat suatu hadits bisa dengan bertanya kepada para ulama ahli hadits. Sebab merekalah yang punya kemampuan dan kapasitas dalam melakukan penelusuran sanad dan perawi suatu hadits serta menentukan derajatnya.
Setiap hadits itu harus ada alur sanadnya dari perawi terakhir hingga kepada Rasulullah SAW. Para perawi hadits itu menerima hadits secara berjenjang, dari perawi di atasnya yang pertama sampai kepada yang perawi yang ke sekian hingga kepada Rasulullah SAW.
Seorang ahli hadits akan melakukan penelusuran jalur periwayatan setiap hadits ini satu per satu, termasuk riwayat hidup para perawi itu pada semua level / tabaqathnya. Kalau ada cacat pada dirinya, baik dari sisi dhabit (hafalan) maupun `adalah-nya (sifat kepribadiannya), maka akan berpengaruh besar kepada nilai derajat hadits yang diriwayatkannya.
Sebuah hadits yang selamat dari semua cacat pada semua jalur perawinya hingga ke Rasulullah SAW, dimana semua perawi itu lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai perawi yang tisqah, maka hadits itu dikatakan sehat, atau istilah populernya shahih. Sedikit derajat di bawahnya disebut hadits hasan atau baik. Namun bila ada diantara perawinya yang punya cacat atau kelemahan, maka hadits yang sampai kepada kita melalui jalurnya akan dikatakan lemah atau dha`if.
Para ulama mengatakan bila sebuah hadits lemah dari sisi periwayatannya namun masih tersambung kepada Rasulullah SAW, masih bisa dijadikan dalil untuk bidang fadhailul a`mal, atau keutamaan amal ibadah.
Sedangkan bila sebuah hadits terputus periwayatannya dan tidak sampai jalurnya kepada Rasulullah SAW, maka hadits ini dikatakan putus atau munqathi`. Dan bisa saja hadits yang semacam ini memang sama sekali bukan dari Rasulullah SAW, sehingga bisa dikatakan hadits palsu atau maudhu`. Jenis hadits yang seperti ini sama sekali tidak boleh dijadikan dasar hukum dalam Islam.
Untuk mengetahui apakah sebuah hadits itu termasuk shahih atau tidak, bisa dilihat dalam kitab susunan Imam Al-Bukhari yaitu shahih Bukhari atau Imam Muslim yaitu shahih muslim. Untuk hadits-hadits dha’if juga bisa dilihat pada kitab-kitab khusus yang disusun untuk membuat daftar hadits dha’if.
Di masa sekarang ini, para ulama yang berkonsentrasi di bidang hadits banyak yang menuliskannya, seperti karya-karya Syaikh Nashiruddin Al-Albani. Di antaranya kitab Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah yang berjumlah 11 jilid.
struktur hadits terdiri atas dua komponen utama yakni sanad/isnad (rantai penutur) dan matan (redaksi).
Contoh:Musaddad mengabari bahwa Yahyaa sebagaimana diberitakan oleh Syu’bah, dari Qatadah dari Anas dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: “Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri” (Hadits riwayat Bukhari)
1 komentar Desember 28, 2010